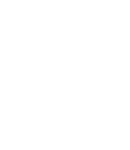Suara gaduh di sekitarku membangunkanku dari lelapnya tidur. Aku merenggangkan otot-otot tubuhku. Aahhh….enaknya, entah kenapa kasurku berubah menjadi begini empuk. Aku membuka mataku, terpampang di hadapanku kursi-kursi yang tertata rapi dan seorang pramugari yang sedang berbicara yang aku sama sekali tidak tahu maksudnya. Aku memicingkan mata, seingatku, tadi aku berada di atas tempat tidurku, bukan di tempat….yang kalau tidak salah disebut pesawat terbang!
Orang-orang disekitarku sudah terlihat sibuk mengemasi barang-barang bawaannya. Mereka terus saja berisik dan aku terus saja tidak mengerti. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, siapa tahu aku juga membawa barang bawaan. Tapi….kosong, tidak ada apa-apa! Aku benar-benar kesini dengan tangan hampa, dan tempat yang aku sendiri tak tahu persisnya di mana! Sekali lagi, aku menoleh ke orang yang ada di sampingku, aku perhatikan wajahnya baik-baik. Mukanya oval agak panjang sedikit, rambutnya lurus dengan poni yang dibelah ke samping kanan. Dia sudah siap dengan koper bawaannya, lalu menoleh ke arahku yang sedang kebingungan. Dari balik kacamata coklatnya, aku tahu aku pernah melihat wajahnya. Mungkin di majalah atau di internet, dia tak asing bagiku. Dan………
“Shin Hye-sung!” kataku setengah berteriak.
Wajah di depanku terlihat agak terkejut. “Ya, saya Shin Hye-sung. Anda……..eh, salam kenal.” Katanya terbata-bata sambil membungkukkan badan.
Ajaib. Aku mengerti apa yang dia katakan. Padahal tadi aku sama sekali tidak mengerti apa yang orang-orang di sekitarku katakan. Bahkan aku pun baru sekali belajar bahasa korea, tentu saja harusnya belum bisa mengerti apa-apa. “Salam kenal juga. Perkenalkan, nama saya Prima” jawabku. “Peu-ri-ma.” Dia mengeja namaku, walau agak sedikit aneh. Dan itu berarti, dia mengerti bahasaku. Horeee!! Akhirnya bisa juga aku bahasa korea, pasti akan kupamerkan ke teman-temanku. Huh, tunggu kedatanganku!
“Em, Peurima. Kau sama sekali tidak membawa barang bawaan?” tanya Hye-sung
Euforiaku terhenti. Ya, aku memang tidak membawa apa-apa. “Ya, bahkan sejujurnya aku pun tidak tahu kenapa aku bisa ada di sini.” Aku meraba kantong celanaku, kosong. “Dan aku pun tidak membawa uang sama sekali.” Kataku sambil mengangkat bahu.
“Cerita yang aneh.” Kata Hye-sung sambil sedikit tersenyum. “Baiklah. Kalau begitu…kurasa kau bisa ikut bersamaku untuk sementara.”
Mataku terbelalak. Diajak oleh seorang artis? Nggak mimpi nih? Batinku. “Oh, terima kasih. Terima kasih. Anda baik sekali.” Kataku sambil membungkukkan badan. Aneh, sejak kapan aku punya kebiasaan membungkukkan badan jika mengucapkan terima kasih?
“Ayo, ikuti saja aku. Pintu pesawatnya sudah dibuka.” Lagi-lagi perkataannya memecah euforiaku. Aku hanya mengangguk, lalu mengikuti langkahnya. Dalam perjalanan menuju pintu keluar pesawat, aku terus asja memegangi kedua pipiku, daguku, keningku, mataku, pokoknya segala anggota wajahku dengan kedua tanganku. Apa aku ini bermimpi ya? Tapi ini sungguh-sungguh nyata, bahkan tadi aku merasakan pesawat yang sedikit terguncang saat mau mendarat. Bau badan Hye-sung pun jelas-jelas tercium oleh hidungku. Ya ampun, mimpiin dia juga Cuma sekali, kok bisa ketemu gini ya? Batinku.
Saat kami berdua melepaskan kaki kami dari anak tangga terakhir, puluhan jepretan kamera langsung menyerbu kami, tepatnya Hye-sung.
“Hye-sung, apakah pembuatan albummu telah selesai? Sepertinya kau pulang lebih cepat dari yang dijadwalkan?”
“Kabarnya di Inggris sana kau sempat menjalin hubungan denga seorang gadis biasa di sana? Apakah itu benar?”
“Kenapa sekarang Anda sering terlihat sendiri. Apakah Shinhwa memang terancam bubar?”
Pertanyaan-pertanyaan dari watawan itu sedikit banyak memusingkan kepalaku. Seperti tahu keadaanku, Hye-sung berbalik ke arahku, lalu menggandeng tanganku cukup erat. Aku jelas kaget, mukaku bersemu merah.
“Jangan pedulikan mereka.” Katanya.
Tapi dengan kejadian itu, para wartawan malah semakin gencar menanyai kami.
“Hye-sung, apakah ini kekasih barumu? Tapi wajahnya seperti wajah wanita Asia Tenggara, bukan Britania seperti yang ramai dibicarakan orang?”
“Mohon beri penjelasan ke kami. Apakah wanita di sampingmu itu benar-benar kekasihmu?”
“Hye-sung, kami mohon penjelasan.”
Lalu tiba-tiba sekelompok orang berbadan kekar dengan tuksedo dan kacamata hitam menghampiri kami. Mereka melindungi kami dari gencaran para wartawan.
“Permisi. Mohon jangan ganggu kami.” Seru mereka berulang kali. Para wartawan itu menyingkir dengan wajah kecewa. Sementara itu, Hye-sung makin mengeratkan genggamannya bahkan menarik diriku lebih dekat dengannya. Badanku panas dingin. Ya ampuunnn….ampun dah!
Akhirnya para wartawan itu sudah tidak mengejar kami lagi. Aku menghela napas lega. Dan saat aku melihat pemandangan bandara di sekelilingku, woow! Aku benar-benar takjub. Bandara Incheon, Seoul, benar-benar indah, dengan dinding-dinding kaca yang futuristik menghilangkan semua lelahku. Di balik pintu, kulihat lima personil Shinhwa lainnya melambaikan tangan ke arah kami. Hye-sung pun membalas lambaian mereka, begitu juga aku. Nggak apa-apalah, sekali-kali melambaikan tangan ke artis, kan belum pernah, batinku nakal.
“Yuk, kita ke mereka.” Ajak Hye-sung. Aku mengangguk, lalu melangkah riang. Saat tanganku meraih gagang pintu keluar, tiba-tiba saja aku sudah berada di tengan kerumunan orang banyak di jalan raya. Kali ini aku kaget lagi. Orang-orang di sekitarku memandang ke arah kumpulan para cowok di depan mereka dengan takjub. Aku pun menoleh ke arah yang sama. Dan…ya ampun! Mataku terbelalak lagi. Super Junior! Ya, itu kan Super Junior! Mereka sedang mengadakan “Free Hug”, artinya siapa saja boleh memeluk mereka. Ya ampun? Aku melihat Choi Shi-won yang sedang tersenyum manis, Han Kyung yang begitu seksi, Dong-hae yang tampan. Tanpa sadar aku berlari ke arah mereka, tepatnya ke arah Han Kyung. Melihatku, dia membuka tangannya dan memelukku dengan manis.
“Aahh…Han Kyung! Aku senang banget bisa dipeluk sama kamu!” Teriakku padanya.
Dia hanya tersenyum manis, membuatku terlihat bodoh. Lalu Shi-won, Dong-hae, Lee Teuk, Ryeo-wook, Eun-hyuk, Shin-dong, Ye-sung, Kyu-hyun, Sung-min, Hee-Chul, Kang In, dan Ki-bum mengeliliku. Mereka semua tersenyum padaku.
“Seoul-e eoseo oseyo[1].” Kata mereka.
Aku berteriak kegirangan, “Gomawo[2].” Kataku. Aku terus memandangai mereka. Aduh, mereka begitu tampan, pikirku. Namu, tiba-tiba orang-orang yang tadinya diam berlarian ke arah kami. Aku terkejut, aku seperti tidak bisa menggerakkan tubuhku, terlalu banyak orang.
Tubuh-tubuh yang membawa ransel itu terus mendorong-dorong tubuhku. Tubuhku menjadi tidak seimbang, dan hampir terjatuh kalau saja seseorang tidak mengyangga tubuhku. Dia menarik tanganku dan dibawanya berlari.
“Hey, Peurima, ayo cepat!” kita hampir terlambat, nih!” kata seorang anak perempuan yang menarik tanganku tadi. Dia terus mengajakku berlari sambil terus memperhatikan jam di pergelangan tangannya.
“Aduh, pelan sedikit dong, Soo-jung!” aku menutup mulutku, heran sendiri. Darimana aku tahu namanya, batinku. Aku melihat pakaianku, dan aku kembali terkejut. Di mana celana jeans dan kaos t-shirt yang tadi kukenakan? Kenapa sekarang berganti menjadi seragam krem dan rok biru kota-kotak? Pikirku. Aneh, hari ini benar-benar banyak kejutan!
“Ah, udah deh.” Katanya lagi. Dia terus mengajakku berlari menyusuri lorong-lorong sekolah yang terasa begitu panjang. Di perempatan kedua, kami belok kiri. “Nah, akhirnya sampai juga.”
Kami masuk ke dalam kelas. Murid-muridnya banyak yang mengobrol, ada yang melamun, ada yang bermain hp, bahkan ada yang bermain pesawat terbang dari kertas! Rupanya tidak ada guru. Kami menarik napas lega.
“Huh, tu kan nggak ada guru. Kenapa coba tadi buru-buru segala?” gerutuku pada Soo-jung.
“Yah, mana ku tahu kalo nggak ada guru. Biasanya kan guru sudah menunggu di kelas. Tumben banget nih nggak ada guru kayak gini.” Balasnya.
Aku segera menuju bangkuku yang berada di bagian belakang kelas, menaruh tasku di atas meja, lalu duduk. Aku mengusap keringat yang membanjiri tubuhku. Ternyata di Korea kalau tidak ada guru ribut juga, batinku. Tak sengaja ekor mataku menangkap seorang lelaki yang duduk di bingkai jendela. Bingkai jendela itu berukuran agak panjang, jadi bisa diduduki. Matanya menatap kosong ke luar kelas. Aku menatapnya dengan seksama sambil mengucek-ucek mataku. Won-bin? Betul Won-bin nih? Bagaimana mungkin dia ada di sini?
Aku mengalihkan pandanganku ke Soo-jung, “Hey, ini SMA Seongji ya?” tanyaku.
Soo-jung menatapku heran, “Kamu ini bagaimana sih? Masak lupa sama sekolah sendiri. Ya iyalah, ini SMA Seongji, memangnya kamu pikir di mana?”
Aku hanya terdiam, seingatku sekolahku di SMA N 1 Metro, pikirku. Tapi ini….., ya sudahlah. Aku tambah pusing kalau memikirkannya. Aku mengarahkan lagi pandanganku ke arah Won-bin. Tanpa ku duga, mata kecilnya menatap ke arahku, lalu dia tersenyum manis, yang membuatku ingin pingsan.
Aduh, aku jadi salah tingkah dibuatnya. Bagaimana tidak? Ditatap oleh seorang artis yang ku idolakan? Aku sendiri pun bingung, apa aku ini bermimpi? Segala yang ada di hadapanku benar-benar terlihat nyata, tapi semua peristiwa yang terjadi seperti mustahil bagi seorang Prima, pikirku.
Won-bin pun turun dari bingkai jendela, lalu duduk di dekatku. Hatiku jadi dag-dig-dug dibuatnya. Dia memegang pergelangan tanganku dengan lembut dan menggeser sedikit lengan bajuku. Mukaku semakin memerah diperlakukan olehnya seperti itu.
Cukup lama Won-bin memandangi pergelangan tanganku sebelum akhirnya berkata dengan wajah sumringah, “Ternya kamu benar-benar cucunya Lee Dong-wook. Tanda yang kakek ucapkan benar-benar ada di pergelangan tanganmu.”
Aku melongo, lalu melihat pergelangan tanganku. Ada tanda berbentuk seperti tetesan darah berwarna hitam di sana. Aku heran, sejak kapan aku punya tanda seperti itu? Dan lagi, apa tadi, cucunyaLee Dong-wook?
“Apa katamu tadi? Aku cucunya Lee Dong-wook?”
“Ya. Tanda yang diceritakan kakek benar-benar mirip dengan yang ada di pergelangan tanganmu. Aku jadi teringat padamu saat kemarin kakek menceritakan itu padaku.”
“Apa? Lee Dong-wook kakekku?” aku masih saja heran, “Memangnya kapan dia menikah, kok aku belum tahu beritanya? Dia juga kan masih umur 27, masak sudah punya cucu? Sebesar aku lagi? Anak saja rasanya tak mungkin.”
“Itulah kelebihan kakek. Sejak istrinya meninggal, tiba-tiba saja dia memanggil semua cucunya yang mempunyai tanda seperti itu. Publik waktu itu sempat kaget dengan pengakuannya bahwa dia sudah mempunyai cucu. Aku pun dipanggilnya karena aku juga mempunyai tanda seperti itu.” Jawabnya lagi sambil memperlihatkan tanda yang sama persis di pergelangan tangannya.
“Aduh, kok aneh banget sih? Nggak masuk akal?” kataku. Tapi tiba-tiba aku menggelengkan kepalaku, “Aku tidak mau. Aku tidak rela menjadi cucu dari seorang Lee Dong-wook! Aku masih punya kakek di rumah. Aku tidak mau. Pokoknya tidak!” teriakku, air mata mulai menggenang di kedua pelupuk mataku. Aku sendiri kembali terheran, alasanku benar-benar tidak masuk akal, tapi kenapa aku bisa sampai menangis seperti ini? Apakah aku memang benar-benar membenci Lee Dong-wook, sehingga tidak mau menjadi cucunya?
Kulihat Won-bin menatapku sedih, “Dia sayang padamu. Kau adalah cucu terakhir yang benar-benar didambanya. Dia sangat…” kata-kata Won-bin tak sempat terselesaikan karena seorang guru memasuki kelas kami. Semua murid sibuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Won-bin pun kembali ke bangkunya yang berselang dua bangku dari kiri tempat dudukku. Rupanya jam pelajaran pertama sudah habis. Kami pun kembali mengikuti pelajaran. Selama itu, Won-bin terus menatapku dengna tatapan mengharap. Aku jadi tidak bisa berkosentrasi dengna pelajaran.
Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Aku segera membereskan buku-bukuku, lalu segera keluar kelas. Baru beberapa meter keluar dari kelas, Won-bin kembali mencegatku. Dia memegang tanganku. Aku menatapnya. Kami sama-sama terdiam, lalu berjalan bersama. Kami menyusuri lorong-lorong sekolah yang panjang untuk bisa sampai ke halaman sekolah.
“Sebenarnya, apa alasanmu sehingga kau bersikeras tida mau menjadi cucu kakek? Tanda yang ada di tanganmu itu merupakan satu-satunya bukti bahwa kau adalah cucunya. Jangan takut, dia akan memberimu segalanya.” Perkataan Won-bin membelah sunyi di antara kami.
Aku melihat tanda yang ada di pergelangan tanganku. Mengutuknya. Gara-gara tanda ini, aku harus menjadi cucunya Lee Dong-wook, batinku sambil menggosok-gosok tanda tersebut.
“Aku, aku, hanya ingin hidup bebas seperti sekarang ini? Aku tidak pernah suka menjadi cucu seorang artis atau konglomerat. Kehidupan mereka akan selalu menjadi sorotan publik. Aku juga tidak pernah menyukainya, gara-gara temanku terlalu menyukainya.” Aku jadi teringat kehidupanku di Indonesia. Aku teringat Tina yang begitu menggilai Lee Dong-wook sehingga aku agak segan dengan artis tersebut. Aku teringat Ayah dan Ibu, juga Leni, adikku yang suaranya seolah-olah bisa merusak tatanan bintang di langit. Ayah, ibu, kenapa aku bisa berada di Seoul seperti ini? Aku memang bercita-cita ke sini tapi aku tak pernah mau menjadi cucu dari seorang aktor. Aku lebih menyukai kehidupanku yang seperti biasa, yang seperti kemarin. Tuhan, kenapa aku bisa di sini? Jerit batinku.
Di halaman sekolah, aku menangis di pinggir kolam yang airnya begitu jernih. Aku berkaca di atasnya. Won-bin masih menanti di sampingku.
“Peurimadoona. Itu kan nama panjangmu? Kau sekarang menajdi primadoona untuk kakekku, kakek kita. Ayolah Peurima. Kakek sudah beberapa hari in sakitnya kembali kambuh karena memikirkanmu. Ayolah.” Bujuknya lagi.
Sebuah limousine hitam mengkilap masuk ke halaman SMA Seongji. Empat orang bertuksedo perak keluar dari sana. Mataku menatap tak percaya ke arah mereka. Min-hwan, Jong-hun, Hong-gi, dan Jae-jin! Aku tak menyangka kelim apersonil FT Island itu (ditambah Won-bin) ada di hadapanku. Mau apa mereka ke sini? Aku menatap ke arah Won-bin, seakan bertanya padanya.
Won-bin seakan tahu apa pertanyaanku, “Mereka ke sini mau menjemput kita. Kakek sudah menunggu.”
“Mereka juga cucunya Lee Dong-wook?” tanyaku.
Won-bin hanya mengangguk. Aku jadi berubah pikiran, kelima personil FT Island yang aku idolakan itu cucunya Lee Dong-wook, kalau aku jadi cucunya juga, itu berarti aku akan sering bersama mereka. Aha..
Aku menatap Won-bin dengan sumringah. “Won-bin, aku mau menjadi cucunya Lee Dong-Wook.”
Won-bin menatapku tak percaya, “Kau serius?”
Aku hanya mengangguk, sambil tersenyum. Lalu pandanganku kualihkan kearah empat orang tadi, “Mereka jadi tukang antar jemput? Jadi bodyguard gitu?” tanyaku lagi.
Jong-hun yang mendengar perkataanku langsung menyela,”Kalau saja bukan karena permintaan kakek, mana mau kami seperti ini?”
“Iya. Mana aku belum terlalu bisa mengendarai limousine ini. Kalian tadi nggak spot jantung kan?” Hong-gi menimpali sambil melirik ke-3 rekannya. Ketiga-tiganya langsung menjitak kepala Hong-gi.
“Tadi itu kita hampir mau ditilang polisi gara-gara kamu mengendarainya sembarangan, tahu!” ujar Jae-jin.
“Iya, nanti Jong-hun sajalah yang menyetir. Tadi polisi itu sudah nguber-nguber kita, pasti juga dah kenal sama mobil kita. Limousine kita kan unik.” Sewot Min-hwan.
Aku dan Won-bin hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Won-bin memegang tanganku. “Ayo masuk.” Ajaknya. Aku pun tak bisa menolak lagi permintaannya. Mungkin aku harus menghapus kesan negatif terhadap Lee Dong-wook dari pikiranku karena sekarang impianku untuk bisa bersama dengan FT Island akan terwujud.
Kami semua akhirnya masuk ke dalam limousine. Jong-hun dan Hong-gi di depan, Min-hwan dan Jae-jin di belakang, sementara Won-bin dan aku di bagian belakang. Limousine melaju pelan menuju kediaman kakek Lee Dong-wook.
Akhirnya kami sampai juga. Saat aku keluar, aku melihat pemandangan yang menakjubkan (lagi). Jujur, baru kali ini aku memasuki rumah yang begitu megah dan besar, jauh dari rumah sederhanaku di Indonesia sana. Pohon-pohon besar menghiasi halamannya yang tertutupi rumput yang hijau lembut. Di tepi-tepi jalan setapaknya terdapat semak-semak yang dibentuk sedemikian rupa. Bahkan ada patung Harubang[3] yang terbuat dari es disitu!
Pintu besar berwarna krem sudah terbuka menyambut kedatangan kami. Mereka berlima menyuruhku masuk ke dalam. Walau sedikit ragu, aku pun masuk ke dalam, kosong. Namun tiba-tiba seorang berkursi roda datang dengan didorong oleh pengawalnya menghampiriku. Lee Dong-wook, dengan muka yang agak sedikit pucat. Dia tersenyum melihatku.
“Kau benar-benar mirip dengan istriku, Lee Da-hae.” Dia meraih tanganku dan melihat tanda itu di sana. Senyumnya makin mengembang. “Gara-gara semakin memikirkanmu, aku jadi menunda syuting serial Meteor Garden versi Korea.” Tangannya membuka, mengisyaratkan aku agar dipeluknya. Dan aku benar-benar memeluknya.
Min-hwan, Jong-hun, Hong-gi, Jae-jin, dan Won-bin terdiam melihat aku dan kakek. Won-bin menarik tanganku dan mengajakku ke tepi kolam. Dia menatapku lembut, lalu memegang kedua tanganku dengan erat. Kulihat wajahnya agak sedikit tegang, sepertinya dia akan mengatakan sesuatu padaku.
“Emm, Peurima, kuharap kau mengerti akan pe….” Perkataannya terhenti karena tiba-tiba seorang pelayan wanita memukul lonceng sebagai isyarat untuk makan. Bunyinya begitu keras sampai ke telingaku. Entah kenapa semua ingatanku dipaksa mundur. Saat aku ditatap oleh Won-bin, saat aku ditarik Soo-jung menuju kelas, lalu saat para personil Super Junior mengerumuniku, saat Han Kyung memelukku, saat Hye-sung dan aku berada di pesawat, saat aku merasakan bahwa keempukan kasurku lain dari yang biasanya….
Bunyi lonceng itu semakin lama menjadi seperti bunyi pintu yang dipukul dengan keras. Makin lama bunyi itu semakin gaduh saja. Aku semakin tak tahan.
“Aaah! Berisik amat sih!” teriakku. Mataku terbuka, aku kaget. Kini aku berada di atas tempat tidurku. Aku menepuk keningku. Yah, cuma mimpi. Kenapa sih ibu ini pake gedor-gedor pintu segala, padahal Won-bin dah mau nyatain perasaannya ke aku. Padahal sebentar lagi aku bisa terus bersama personil FT Island.
“Prima, sampai kapan kamu mau tidur, hah? Sudah jam tujuh!” suara khas ibuku membuat lamunanku terhenti.
“Prima, sudah jam tujuh. Cepat bangun!” teriak ibuku lagi.
Aku beranjak dari tempat tidur dengan kesal, lalu membuka pintu.
“Ibu ini, orang lagi mimpi indah-indah juga dibangunin. Kesel tahu!” kataku
“Yah terus kalau kamu mimpi terus kapan mau berangkat sekolah?”
“Ya emang ini jam berapa?”
“Kamu ini telinganya ditaruh di mana sih? Dari tadi ibu sudah berbusa-busa teriak jam tujuh, kamu nggak dengar?”
“Apa bu? Jam tujuh?” teriakku, tanpa menunggu jawaban, aku segera berlari ke arah kamar mandi, tapi lalu kembali ke kamar tidur untuk mengambil baju sekolah. Ya ampun, pikirku. Kenapa sih mimpi indah harus selalu ada resikonya, telat!
Tanpa sarapan dan tanpa pamit, aku segera berlari keluar rumah. Hye-sung, Super Junior, dan FT Island sudah tidak lagi mampir di benakku karena yang sekarang ada adalah, aku akan terlambat!
Metro, 3 April 2008
Saat bayangan-bayangan yang mampir di otakku terlalu banyak,
Dan saat polaris pun lelah menungguku menyelesaikan cerita ini.
[1] Selamat datang di Seoul
[2] Terima kasih banyak
[3] Sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang-orang di Pulau Cheju.
Wanna More.?
Selasa, 22 April 2008
Jangan Bikin nie Bangsa Semakin Ancur, donk!
Yah, kayak yang udah kita tau, akhir2 ini lagi heboh-hebohnya berita about JuPe (a.k.a Julia Perez) en Dewi Persik. Kok heboh? Yah, gimana nggak? Mereka sendiri yang bikin kehebohan kayak gitu!
Pencekalan Dewi Persik sih kalo q bilang wajar2 aja. gimana nggak? Lha wong dia narinya kayak gitu, yang potong gergajilah, belah semangkalah, apalah. Kayak gitu kan ngundang syahwat banged.... Wajarlah kalo di kalo di Bandung dicekal. Emang, pencekalan Dewi Persik bukan jaminan kalo moral masyarakat Bandung bakalan baek baek aja. Tapi gimana langkah kita biar moral masyarakat yang udah terpuruk seenggak-enggaknya nggak keliatan terpuruk.
Terus, ada yang menghubungkan pencekalan itu sama hak wanita yang dibatasi. Ada yang bilang, itu kan cara dia buat nyari nafkah, kok dicekal?
Kalo pendapatQ, kenapa sie Qt harus nyari nafkah pake cara begituan, gak ada tah cara lain, yang lebih bagus, yang lebih nyar'i. Inget surat Ad-Dhuha ayat 3, yang artinya, "Dan Dia tidak akan meninggalkan engkau, dan tidak pula membencimu"
Allah dah menegaskan bahwa Dia nggak akan meninggalkan hamba-Nya, asal Qt mau berusaha en berdo'a, jalan laen pasti ada.
trus about JuPe, masa' dia bagi2 kondom di album barunya?
hah, ide gila apa ini?
ngedukung free sex banged sie?
tapi, masalah kalo dia ngedukung free sex itu, dia bilang kalo gak masuk akal kalao dia disebut ngedukung free sex. katanya, kondom itu di mana-mana ada, di warung kecil, di apotik, harganya tu cuma lima ribuan kita bisa dapet lima. sedangkan kalo belim album JuPe seharga 30 ribu cuma dapet satu, itu gak logis banget kalo dia dianggap ngedukung free sex.
okey, memang gak logis kalo dipikir pake otak, mikirnya pake hati donk! Dia itu kan public figure, yang udah pasti bakalan ditiru sama banyak orang.
Udah deh buat para artis, aktor, en public figure laennya. Dunia artis bisa dilalui tanpa harus make hal-hal aneh dan gak betul kayak gitu?
Kayak yang udah Q sampein tadi, asal Qt berdo'a en usaha keras, tangan-tangan-Nya pasti bakalan bantu Qt melalui kehidupan ini. tanpa harus pake cara-cara haram. Wanna More.?
Pencekalan Dewi Persik sih kalo q bilang wajar2 aja. gimana nggak? Lha wong dia narinya kayak gitu, yang potong gergajilah, belah semangkalah, apalah. Kayak gitu kan ngundang syahwat banged.... Wajarlah kalo di kalo di Bandung dicekal. Emang, pencekalan Dewi Persik bukan jaminan kalo moral masyarakat Bandung bakalan baek baek aja. Tapi gimana langkah kita biar moral masyarakat yang udah terpuruk seenggak-enggaknya nggak keliatan terpuruk.
Terus, ada yang menghubungkan pencekalan itu sama hak wanita yang dibatasi. Ada yang bilang, itu kan cara dia buat nyari nafkah, kok dicekal?
Kalo pendapatQ, kenapa sie Qt harus nyari nafkah pake cara begituan, gak ada tah cara lain, yang lebih bagus, yang lebih nyar'i. Inget surat Ad-Dhuha ayat 3, yang artinya, "Dan Dia tidak akan meninggalkan engkau, dan tidak pula membencimu"
Allah dah menegaskan bahwa Dia nggak akan meninggalkan hamba-Nya, asal Qt mau berusaha en berdo'a, jalan laen pasti ada.
trus about JuPe, masa' dia bagi2 kondom di album barunya?
hah, ide gila apa ini?
ngedukung free sex banged sie?
tapi, masalah kalo dia ngedukung free sex itu, dia bilang kalo gak masuk akal kalao dia disebut ngedukung free sex. katanya, kondom itu di mana-mana ada, di warung kecil, di apotik, harganya tu cuma lima ribuan kita bisa dapet lima. sedangkan kalo belim album JuPe seharga 30 ribu cuma dapet satu, itu gak logis banget kalo dia dianggap ngedukung free sex.
okey, memang gak logis kalo dipikir pake otak, mikirnya pake hati donk! Dia itu kan public figure, yang udah pasti bakalan ditiru sama banyak orang.
Udah deh buat para artis, aktor, en public figure laennya. Dunia artis bisa dilalui tanpa harus make hal-hal aneh dan gak betul kayak gitu?
Kayak yang udah Q sampein tadi, asal Qt berdo'a en usaha keras, tangan-tangan-Nya pasti bakalan bantu Qt melalui kehidupan ini. tanpa harus pake cara-cara haram. Wanna More.?
Polaris
 Polaris adalah bintang utara yang biasa menjadi penunjuk arah bagi para musafir. Dan ia selalu pada tempatnya, setia.
Polaris adalah bintang utara yang biasa menjadi penunjuk arah bagi para musafir. Dan ia selalu pada tempatnya, setia.”Rin, aku ingin terbang ke Polaris.”
Rina langsung terbangun, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ya, mimpi itu datang lagi. Masih dengan kalimat yang sama dari seorang Andin, teman semasa SD-nya dulu. Dan yang ini sudah ketiga kalinya Rina mendapat mimpi itu. Rina mendesah, perasaannya sudah tak enak sejak pertama kali ia bermimpi seperti itu.
Rina melirik jam weker di samping tempat tidurnya, jam ½ 6. Dengan tergesa, Rina pergi ke kamar mandi. Sejak mimpi itu datang, ia selalu tak mendapat kesempatan untuk shalat malam. Bahkan pada saat mandi dan shalat pun mimpi itu masih membayangi pikirannya.
”Bu, ibu masih inget sama Andin?” tanya Rina pada ibunya saat mereka sarapan.
”Andin?” keningnya berkerut saat mendengar pertanyaan Rina.
”Itu lho bu, temen Rina pas SD. Yang sering main ke rumah, yang jago taekwondo itu.”
“Ooo, yang rambutnya sering diekor kuda itu ya?”
”He-eh. Kok tiba-tiba Rina keinget terus sama dia ya bu?”
”Kangen kali. Udah berapa tahun coba kamu gak ketemu dia kan?” jawab ibunya
7 tahun. Sudah 7 tahun dia tidak bertemu dengan Andin hingga kini ia duduk di kelas 1 SMA.
”Yee, dasar pincang!”
”Kita lomba adu lari yook!”
Cemoohan-cemoohan seperti itu menyambutnya saat pertama kali masuk ke ruangan kelas 4 SD N 1 Palembang. Rina meringis, air matanya seakan sudah tak betah berada di dalam kelopak matanya. Di sekolah sebelumnya, dia tak pernah mendapat ejekan seperti ini.
”Heh, kok diem aja? Nangis ya?” seorang anak laki-laki bertubuh gempal menyadarkan lamunannya.
”Kan katanya larimu cepat. Kayak....” ”Kayak siput.” yang lain menimpali.
Dan air mata Rina pun tak terbendung lagi. Ia menangis. Jika saja ia tak sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan banyak orang, mungkin kruk yang menyangga tubuhnya sudah terlepas. Namun air matanya semakin deras mengalir, tatkala suara-suara tawa di hadapannya memenuhi gendang telinganya.
”Heh, kalian ini apa-apaan sih? Beraninya ganggu orang yang lemah.” sebuah teriakan menggema di ruangan kelas itu. Suara tawa mendadak hilang, sebab seseorang yang biasanya tukang biang onar menolong seseorang yang sedang diejek.
Anak itu mendekati Rina sambil menyapanya lembut. ”Kamu gak papa kan? Maafin mereka ya, anak-anak kelas ini hobinya itu.”
Rina menggeleng pelan, lalu mencoba membenarkan letak kruk yang hampir terjatuh.
”Namaku Andin.” katanya sambil mengulurkan. ”Aku udah tahu namamu. Nggak usah ngenalin lagi, Rina. ”
Rina terheran. Andin yang melihat hal itu berkata, ”Kamu kan tadi udah kenalan di depan kelas, jadi nggak usah ngenalin diri lagi.” jelasnya sambil tersenyum. Dan Rina pun ikut tersenyum.
”Heh, Andin! Ngapain kamu temenan sama anak cacat kayak dia. Kamu pasti nyari mangsa baru buat dapet contekan. Iya kan?” suara si gempal itu lagi, yang disambut tawa riuh anak sekelas.
Bak, Buk! Rina terkaget, si gempal itu langsung dipukul oleh Andin.
”Heh, jangan main-main ya! Aku kali ini tulus nolongin dia! Nggak kayak kamu, yang kalo temenan pasti punya maksud. Awas kamu kalo sampe nyakitin dia.....” jawab Andin sambil meremas-remas jari tangaanya.
Lalu tawa-tawa itu berhenti bergaung. Siapa pun tahu kalau Andin jago taekwondo. Sudah sering ia mengikuti kejuaraan-kejuaraan taekwondo di kota Palembang.
Dan sejak itu, Rina pun bersahabat dengan Andin. Andin memang tidak pintar, ia sering menyontek pekerjaan Rina jika otaknya sudh tidak mampu lagi mencerna penjelasan dari guru ataupun Rina yang mencoba membantunya, yang membuat Rina hanya geleng-geleng kepala. Tapi, di balik sikapnya yang begitu tomboi, Andin pintar membuat puisi yang sering diberikannya kepada Rina. Dan satu lagi yang membuat Rina tak ragu bersahabat dengan Andin, karena tali persahabatan yang diulurkan Andin begitu tulus
”Din, aku boleh tanya gak?” kata Rina siang itu seusai sekolah.
”Hmmm......” jawab Andin singkat, ia masih asyik memainkan kaki-kakinya di telaga kecil di belakang sekolah. mereka memang sering pergi ke situ sepulang sekolah sambil kadangkala mengerjakan tugas yang diberikan guru. Atau hanya untuk bermain-main.
”Kenapa kamu mau berteman sama anak cacat kayak aku ini?”
Andin menatap Rina dalam. Lalu pandangannya dialihkan ke air telaga yang memantulkan bayangan wajahnya.
”Aku cuma gak penging kamu kayak adikku”
”Kamu punya adik?”
”Dulu. Dia juga cacat kayak kamu. Dan dia meninggal gara-gara tidak ada kepedulian dari orang tua kami. Aku juga dulu jarang bermain dengannya. Setelah dia nggak ada, aku baru sadar kalo aku butuh teman di rumah dan teman itu udah gak ada.” jelas Andin. ”Dan aku gak mau kehilangan teman lagi.”
Rina terdiam. Lalu memegang lembut bahu Andin.
”Rina, bisa kamu sebutkan di mana saja habitat Paramaecium?” Nina yang duduk di sebelah Rina menyenggol pelan siku Rina. Namun, rupanya alam pikiran rina masih melayang di antara telaga kecil di belakang sekolahnya dulu.
”Rina?” Pak Rudi, guru biologi, mengulangi panggilannya.
”Rin, ditanya Pak Rudi tuh.”
Dan Rina pun tersadar dari lamunannya. ”Eh, iya Pak. Di telaga belakang sekolah, Pak.” jawabnya asal. Jawaban Rina itu kontan membuat seisi kelas tertawa. Dan rina menyadari bahwa lamunannya terlalu lama untuk berada di dalam kelas. Rina pun menunduk dengan muka memerah karena malu.
”Kamu sedang mikir apa sih rina? Akhir-akhir ini kamu sering melamun, Bapak Khawatir nanti nilaimu pada turun.” nasihat Pak Rudi.
”Maaf, Pak. Lain kali saya tidak akan melamun lagi.”
Dan Pak Rudi pun melanjutkan pelajarannya tanpa memperpanjang masalah itu.
-Tuhan...
Bisa kah Kau terbangkan driku merambah jomantara
Lalu.....
Bawa aku ke Polaris
Aku ingin meletakkan semua memori ini
Tentang Ayah,
Tentang ibu,
Tentang semuanya,
Yang buat hidupku tak berwarna
Ku ingin semua itu tak ada, Tuhan
Ku lelah dengan semua itu
Ku ingin meletakkan semua itu di sana, meninggalkannya
Lalu kembali ke sni
Dengan memori baru hiasi diriku
Tuhan, bisakah?
Hanya sebentar, ku takkan lama
Ku takkan lama Tuhan
Tuhan...
Q ingin Polaris-
Rina tertegun, saat melihat pusis di dalam buku Matematika milik Andin. ”Din, ini maksudnya apa sih?” tanyanya.
”Nggak ada maksud, aku cuma pengin pergi ke Polaris.”
”Polaris, apaan tuh?”
”Bintang utara.” jawab Andin singkat
Dan Rina masih juga tak mengerti. Polaris?
”Din, kamu punya masalah ya? Kalo ada ngomong dong?”
”Masak sih Rin? Emangnya aku kelihatan punya masalah?” Andin mematahkan dugaan Rina. Rina terdiam. Ia tahu, Andin memang selalu ceria, seakan tak pernah punya masalah. Tapi Rina masih tak mengerti juga dengan puisi Andin.
-Aku ingin meletakkan semua memori ini
Tentang Ayah,
Tentang ibu,
Tentang semuanya,
Yang buat hidupku tak berwarna
Ku ingin semua itu tak ada, Tuhan
Ku lelah dengan semua itu-
Andin pasti punya masalah, batinnya. Tapi kenapa gak mau ngomong. Dia kan sahabatnya. Sungguh ia ingin katakan semua itu pada Andin, tapi lantaran tak rela melihat ceria di wajah Andin lenyap. Maka Rina pun hanya terdiam.
Andin masih asyik memainkan kakinya di air, sore itu sungguh mesra dengan cahaya jingga yang menyemburat memenuhi langit. Dengan alang-alang yang terus berayun lembut karena angin sepoi. Dan matahari yang seakan tak jua ingin beristirahat. Mereka benar-benar tak ingin meninggalkan telaga sore itu, jika saja mereka tak sadar bahwa orang tua mereka pasti menunggu.
Dan kali itu, adalah saat terakhir Rina melihat wajah ceria Andin. Esoknya, ia tak lagi melihat Andin. Bahkan saat Rina menyambangi rumahnya, hanya sunyi yang menyambut kedatangannya.
”Din, apa kamu sudah terbang ke Polaris?”
Jalanan siang itu sepi. Rina –masih dengan kruknya- berjalan tertatih menyusuri jalanan itu. Rumahnya memang tak jauh dari sekolahnya, yang membuatnya memilih berjalan sat berangkat dan pulang sekolah.Tiba-tiba beberapa anak kecil menghalangi langkahnya.
”Eh, liat deh. Mbak pincang lewat lagi.”
”Pasti kruknya lebih cepet daripada motor, makanya dia pake kruk terus.”
Lalu terdengan tawa-tawa riuh memecah sunyi jalanan. Rina hanya tersenyum. Telinganya sudah kebal mendengar semua itu. Dan ia bertekad tidak akan pernah mengeluh. Rina berhenti sejenak di tempat yang agak sunyi, di dekat kebun mangga milik Pak Amir, mencoba melepaskan lelah yang menderanya. Tiba-tiba ekor matanya menangkap bayangan seorang gadis dengan baju seragam SMA yang dipakai asal-asalan dan ukuran yang diperkecil. Gadis itu –yang tak melihat Rina karena tertutup pohon mangga- dengan perlahan berkata, ”Tuhan, mungkin dengan ini aku bisa terbang ke Polaris.” sambil mengeluarkan silet dari saku roknya.
Lau, dengan sekejap pikiran Rina tentang Andin. Polaris.
”Andin, jangan!” teriak Rina sambil berusaha mendekati Andin.
Gadis itu –Andin- menoleh kaget. ”Rina?”
”Andin, jangan! Jangan lakukan itu!”
Dan Andin pun roboh. Dia bertekuk lutut tak berdaya. Bulir-bulir bening menetes dari kedua mata beningnya.
”Andin, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu bertindak gegabah begini?”
”Rina.......aku tadi hampir menuju Polaris. Kenapa kamu menghentikanku?”
Rina sungguh tak mengerti. Ia benar-benar tak percaya bahwa gadis di hadapannya adalah Andin. Andin yang dulu ia kenal sebagai seorang yang selalu ceria, sebagai seorang yang kuat menghadapi apa pun. Ia benar-benar tak percaya, gadis dengan penampilan urakan dan mata yang terlalu sayu itu benar-benar Andin, teman SD-nya dulu.
”Andin........ini benar-benar kau?”
”Ya. Ini masih aku, Rin. Masih Andin teman SDmu dulu. Masih Andin yang jago taekwondo.”
Rina masih menatapnya tak percaya. ”Din, kamu sekarang tinggal di mana?” tanyanya.
”Aku ingin tinggal di Polaris. Tapi mungkin sekarang kolong jembatan tempat yang pas buatku.”
”Apa?”
Andin tertawa. ”Ya nggaklah, Rin. Rumahku masih yang dulu.”
Rina pun tersenyum. Dia masih Andin yang dulu, yang penuh humor.
”Rin, kamu sekarang pake jilbab jadi tambah putih. Tadi aku sampai pangling. Kamu kan dulu item.” candanya.
Rina cemberut. Bisa-bisanya Andin berkata seperti itu. Rina hampir tak percaya bahwa Andin yang sering bercanda ini tadi hampir bunuh diri.
”Din, tadi kenapa kamu...?” pertanyaan Rina belum sempat terselesaikan karena Andin sudah duluan menyahut, ”Udah dulu ya Rin, aku mau pulang. Ntar dimarahin Papa.”
”Tapi Din, kamu gak bakalan bunuh diri kan?”
Andin hanya mengangkat bahu, ”Kapan-kapan main ke rumah ya?”. Lalu pergi meninggalkan Rina yang terdiam bingung. Pikirannya benar-benar cemas. Andin...jangan bunuh diri. Nanti kamu gak bisa ke Polaris...
Rina menatap langit kelam malam itu. Ah, Andin, di mana Polaris yang kamu cari itu? Kenapa kamu pengin pergi ke sana? Apa yang pengin kamu lakukan di sana? Kenapa aku gak boleh tahu masalah apa yang menimpamu? Kamu masih ngganggep aku sahabatmu kan?. Pertanyaan demi pertanyaan terus membatin di batin Rina. Dan ia benar-benar tak tahu harus bicara apa pada sahabatnya itu.
Sekali lagi, Rina manatap langit malam itu. Tak banyak bintang. Namun entah kenapa ia begitu ingin keluar rumah. Bergegas ia mengambil kruknya yang bersandar pada meja belajarnya. Tak lupa ia mengenakan jilbab untuk menutupi mahkota hitam miliknya.
”Rin, mau ke mana? Tumben-tumbenan keluar malem?” tegur ibunya saat Rina dengan sedikit tertatih menuju pintu depan.
”Cuma mau ke depan kok Bu. Malem ini entah kenapa Rina pengin banget ngeliat langit.
Ibunya terdiam. Melihat langit? Benar-benar suatu hal yang sangat jarang putrinya lakukan.
Rina melangkah keluar. Malam ini langit seakan tak mau berhias diri. Polaris. Di mana Polaris itu? Yang tampak di mata Rina hanyalah beberapa bintang berukuran sama dan berkerlap-kerlip.
”Ah, semua bintang sama. Di mana Polarismu itu Andin?” keluhnya.
”Semua bintang tidak sama, Nona. Harusnya kau pergi ke Observatorium Bosscha kalau ingin membedakan bintang.” sebuah suara yang tidak asing lagi menggetarkan tulang-tulang pendengaran Rina. Ia menoleh. Sosok itu, Andin.
”Andin, ngapain kamu ke sini?” tanya Rina heran.
”Oh, jadi rupanya aku gak boleh main ke sini lagi to? Ya udah, mendingan aku pulang aja.”
””Eh, bukannya gitu. Aku cuma....” Rina jadi merasa tak enak.
”Rina, Rina. Kamu masih sama kayak dulu. Begitu polos kalo diajak bercanda.” Andin tertawa.
”Rin, kamu tahu kenapa aku begitu menyukai Polaris?”
Rina mendekat, kini Andin mau mengungkap sesuatu yang sejak dulu disimpannya. ”Kenapa?”
”Karena Polaris adalah bintang paling setia dan terang. Aku memang hanya pernah sekali melihatnya, tapi ia benar-benar telah mempesonakan mataku. Dia biasa menjadi penunjuk arah bagi para musafir yang tersesat. Dari dulu aku berharap, bisa menemukan Polaris untuk diriku. Dan aku ingin pergi ke sana, mungkin dia akan memberiku petunjuk atas semua ini. Ah, Polaris, bintang utara, aku benar-benar ingin ke sana. Aku ingin meletakkan...”
”Meletakkan semua masalahmu? Sebenarnya kamu punya masalah apa sih?” potong Rina.
Andin yang sedang menatap langit menoleh, lalu tersenyum. Lama, begitu lama. Namun sedetik kemudian, Andin menangis.
Rina panik melihat keadaan sahabatnya yang begitu cepat berubah. ”Din, kamu ngapa? Kok tiba-tiba nangis?”
”Rin, kenapa aku punya masalah begitu banyak, dan dari dulu gak pernah selesai? Aku gak kuat lagi, Rin. Papa sama mama sekarang kerjaannya cuma debat di meja pengadilan, dah gak pernah mikirin aku lagi. Aku sedih Rin, mereka memang dari dulu gak pernah merhatiin aku, tapi aku tetep sedih. Waktu itu aku pergi karena mereka ngajak aku sekolah di Inggris, tapi mereka akhirnya tahu bahwa itu nggak ada artinya. Apalagi, mereka mau membuang diriku. Aku dianggap tak berguna karena masuk jurusan bahasa, gak masuk IPA. Padahal di IPA aku bisa apa Rin? Dan juga Rin, aku hamil.” cerita Andin sambil terisak.
”Apa Din, kamu....kamu hamil?” bagai ada palu godam yang menghantam kepala Rina. Dia sungguh tak menyangka jika sahabatnya terseret kehidupan begitu jauh.
”Aku gak tahu lagi Rin harus gimana. Ku kira rokok, narkoba, ma pacaran bisa ngilangin semua frustasiku. Apalagi temen-temenku udah aku anggap Polarisku. Tapi mereka nggak setia, Rin. Dan gak ada Polaris yang nggak setia. Apalagi si Miko sialan itu, dia pergi gak tahu ke mana setelah nyuruh aku aborsi. Aku gak tahu lagi, Rin. Gak tahu lagi harus sama siapa aku minta tolong?”
”Kamu...udah minta tolong sama Allah, Din?”
Andin menoleh, ”Allah?” tanyanya heran. Rina tersenyum, dia tahu dari dulu bahwa sahabatnya memang jarang mendekatkan diri kepada Allah, bahkan setahu Rina tak pernah. Dan ia menyesal baru bisa mengatakannya sekarang. Ia menyesal kenapa tak dari dulu membantu masalah Andini. Dan memang penyesalan selalu datang di akhir, kala semua peristiwa telah terjadi.
”Iya, Din. Kamu belum minta tolong sama Allah? Cuma Dia yang bisa nolong kamu dari semua masalah kamu. Kenapa kamu gak nyoba dekat dengan-Nya?”
Andin menggeleng pelan, ”Aku udah terlalu lama ngelupain dia Rin, dia pasti udah ngelupain aku. Dan sekarang, saat aku inget, aku udah terlalu banyak ngelakuin kesalahan. Aku udah gak ada artinya di hadapan-Nya. Aku udah terlalu hina, Rin. Mungkin lebih baik aku pergi ke Polaris, di sini gak ada Polaris Rin. Aku bakalan naro semua masalah ini di sana. Aku pingin banget Rin memulai hidup yang baru tanpa mengingat-ingat kembali semua yang telah aku alamin.”
Rina menatap Andin lama. Ia sungguh tak mengerti jalan pikiran gadis itu. Kenapa hanya Polaris yang menurutnya bisa mengeluarkannya dari masalah. Kenapa ia tak berpikir bahwa Allah-lah yang bisa menenangkan hatinya, dan membantunya keluar dari segala masalah ini. Kenapa?
”Nggak Din, kamu nggak boleh berpikir kayak gitu. Andin yang aku kenal dulu adalah Andin yang selalu optimis. Dan Allah, telah menjadi Polaris untukmu Din. Dia bisa membantumu menemukan jalan keluar, Dia selalu setia Din, Dia gak akan pernah ninggalin kamu. Dan nggak pernah ada kata terlambat untuk bertobat bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Dan Dia past mengabulkan tobatmu, mengampuni kesalahanmu, dan memberikan titik terang untuk segala masalahmu Din, percayalah.”
Andin tersenyum, ”Tapi, Rin, aku sudah dekat dengan Polarisku.”
Rina merasakan ada sesuatu yang bergemuruh tak karuan di hatinya, tapi ia tak tahu.
”Rin, aku pulang ya. Udah terlalu malam.”
Rina menatap kepergian sahabatnya dengan perasaan tak menentu. Dan gemuruh itu bergemuruh lebih kencang. Ya Allah, lindungilah ia.
Sesampainya di rumah, Andin merasakan perutnya melilit hebat. Ia menangis. Rupanya baru sekarang obat itu berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Tangisnya semakin deras, sebuah do’a terucap dari lubuk hatinya, ” Ya Allah, Polarisku, apakah dirimu mau memaafkan diriku yang telah membunuh seorang nyawa tak berdosa?”
Sejenak kemudian, dengan tertatih, Andin melangkah menuju ke kamar mandi. Ia belum shalat Isya. Dengan tangan gemetar, diputarnya kran untuk berwudhu. Dan lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, shalat itu pun dilakoni Andin.
Setelah shalat, lilitas di perut Andin semakin mengehebat. Dirinya tak kuasa lagi, ia benar-benar lumpuh total. Namun tangannya masih sempat mengambil secarik kertas dan pena, menuliskan sesuatu di atasnya. Dan setelah itu,
”Asyhadu alla ilaa ha illallah, wa asyhadu annaa muhammadar rasulullah”
mengalir manis dari kedua bibirnya.
”Rin aku sudah sampai di Polaris.”
Mimpi itu datang lagi, dan semakin membuat gemuruh di hati Rina tak karuan. Firasatnya mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu pada Andin. Dengan tergesa-gesa Rina shalat shubuh, lalu menyiapkan peralatan sekolahnya.
”Yah, nanti antarkan aku ke rumah Andin dulu ya?” pinta Rina pagi itu.
”Andin? Teman SDmu itu? Memang rumahnya masih yang dulu?” tanya Ayahnya.
Rina mengangguk. Lalu bergegas menuju halaman untuk menunggu ayahnya siap.
Rumah dengan pagar menjulang itu sepi. Gerbangnya terbuka begitu saja dengn alang-alang di sana-sini.
”Yang ini kan Rin rumahnya? Kok sepi?” tanya Ayahnya.
Tapi tanpa berkata-kata lagi, Rina dengan kruknya bergeas menuju pintu depan. Tanpa pikir panjang, Rina langsung membuka pintu tersebut. Tak dikunci, lalu ia bergegas menuju kamar Andin. Sebuah tubuh tergeletak dengan balutan mukena.
”Andin...Andin, bangun Din.” Rina menggoyang-goyangkan tubuh Andin. Tanpa sengaja Rina melihat secarik kertas dengan sepotong pusisi yang digenggam Andin.
-Ya Rabb,
Turunkanlah kabar gembira bagiku
Di mana bukan hanya Polaris yang menungguku
Namun syurga
Dengan keindahan luar biasa yang mampu
Manjakan mata ini Ya Rabb
Dengan sentuhan cinta di setiap zatnya
Sentuhan cinta-Mu
Ya Rabb,
Ku ingin cinta-Mu
Ku ingin syurga-Mu
Karena kau, Polaris bagiku-
Rina menangis. Sungguh tak kuasa ia mengubah semua keadaan yang ada di hadapannya.
Dan pagi itu sungguh indah. Di mana seorang penanti Polaris telah mendapatkan Polarisnya. Polaris yang begitu setia, dan Dia ada di dekatnya. Dan Dialah, Allah Azza wa Jalla, Sang Pemilik Cinta, telah menurunkan cinta-Nya ke Bumi untuk hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Dan cinta itu sungguh setia, seperti Polaris.
Wanna More.?
Cahaya untuk Ayah

Sore itu, Anni duduk termenung di teras rumahya. Matanya menatap puluhan anthurium dengan beragam ukuran yang ditanam dalam pot di depan rumahnya. Anni memegang sehelai daun anthurium tersebut. Anni menghela nafas, kenapa ayahnya tak henti-hentinya membeli anthurium. Apa sih yang membuat orang-orang begitu menyukai anthurium, bahkan ada yang rela menukarnya dengan mobil mewah.
”Dia sudah seperti pengganti ibumu, Ni.” kata ayahnya saat Anni menanyakan alasan kenapa ayahnya begitu menyukai anthurium.
Anni terdiam. Ibunya memang sudah tiada sejak 6 tahun yang lalu. ”Iya, tapi apa dulu ibu menyukai tanaman ini? Kenapa aya bisa bilang begitu? Kenapa juga ayah rela menukar tanaman-tanaman ini dengan uang tabungan yang sudah ayah kumpulkan bertahun-tahun?” bantahnya.
”Yah, begitulah kalau sudah cinta, Ni.” jawab ayahnya sambil melanjutkan pekerjaannya menanam bibit anthurium yang baru ke dalam pot. Suatu jawaban yang makin membuat kening Anni berkerut karena heran dan bingung.
Lalu mata Anni bergerak ke arah pintu gerbang yang setengah terbuka. Seorang pengemis cilik menatap ke arahnya. Agaknya ia ingin mengemis padanya, namun urung karena dirinya termangu terus sejak tadi. Rasa ibanya muncul, perasaannya memang mudah tersentuh jika melihat pengemis atau gelandangan. Anni berjalan ke arah pengemis itu. Bajunya sudah banyak yang berlubang di beberapa bagian. Mukanya dekil kecoklatan, pertanda bahwa ia sudah bekerja keras sejak pagi.
Anni merogoh kantongnya. Kosong. Ia ingat bahwa uang sakunya telah ia habiskan untuk ongkos angkotnya ke sekolah. ia menatap pengemis itu sekali lagi. Dia sedang memegangi perutnya, ingin menunjukkan bahwa ia lapar.
”Dek, mbak gak punya uang nih. Gimana kalo adek mbak kasih makan aja? Yah?” Pengemis itu mengangguk, tak bisa menolak karena memang perutnya sudah minta diisi sejak pagi tadi. Ia mengikuti saja langkah Anni yang mengajaknya masuk ke dalam rumah.
”Dek, adek duduk di sini dulu ya. Mbak mau ngambilin makanannya.” dan sekali lagi Anni hanya melihat anggukan dari pengemis kecil itu.
Anni bergegas menuju ruang makan dan membuka tudung saji di atas meja. Hanya ada piring kosong bekas tempat menaruh telur ceplok yang ia masak siang tadi. Lalu tangannya bergerak membuka pintu kulkas, ia mengeluh, hanya ada cabai, bawang, dan bumbu-bumbu lain.
”Aduh, masak apaan nih? Masak mau ngasih bumbu sama adek itu?” pikirnya bingung. Tak mungkin ia berkata kepada pengemis itu bahwan di rumahnya tidak ada makanan. Kalaupun bisa setidaknya ia memberikan sedikit uang, tapi sayangnya tak sepeser pun uang digenggamnya saat ini.
Anni berjalan menuju teras belakang. Ekor matanya menangkap beberapa Anthurium yang sengaja ditaruh ayahnya di situ. Tiba-tiba pikirannya terbuka. Ia ingat sebuah berita di koran kemarin bahwa ada seorang ibu yang menjadikan Anthurium sebagai lalapan, yang membuat suaminya langsung terserang stroke. Mungkin anthurium ini juga enak jika ditumis, pikirnya.
Anni mengambil pisau untuk memotong anthurium. Tapi kemudian ia berhenti, jangan-jangan ayahnya nanti akan terserang stroke juga, tapi nggak papa deh, ayah kan punya penyakit stroke. Lalu dengan cepat Anni memotong anthurium itu dan menumisnya. Anni mengambil nasi dan tumisan itu lalu dibawanya ke ruang tamu.
”Dek, maaf ya menunggu la....” kalimatnya tak sempat terselesaikat kala melihat wujud si pengemis sudah tak ada lagi di tempatnya. Ia lupa mengingatkan pengemis itu bahwa dirinya akan memasak dulu. Anni terduduk lemas, satu pahalan untuknya melayang hari ini. Tanpa sadar ia memakan makanan yang disiapkan untuk pengemis itu.
”Enak. Gak nyangka tanaman sekelas anthurium enak juga dibuat tumisan.” dan ia terus melahap makanan tersebut hingga piringnya licin tandas.
Dan malamnya, ia pun menghidangkan tumisan anthurium tersebut pada ayahnya.
”Gimana yah, enak gak?” tanya Anni sambil tersenyum.
”Enak kok. Sayur apa nih namanya?” ayahnya balik bertanya.
Senyum Anni langsung lenyap. Namanya? Tidak terpikir dalam otaknya jika ayahnya akan menanyakan hal tersebut. Tidak mungkin ia menyebut anthurium, bisa-bisa ayahnya langsung naik darah.
”Emm...dak tau yah. Tadi Anni asal ambil aja di warungnya Mbak Surti. Gak sempet nanya namanya.” jawab Anni asal.
”Oh.”
”Yah, boleh gak Anni minta tambahan uang saku. Anni sering kelaparan Yah, gak ada uang untuk beli makanan. Masak Cuma cukup buat bayar angkot pulang pergi?”
”Wah, gak bisa Ni. Rencananya nanti ayah mau beli bibit anthurium lagi. Kamu kan tahu kalo gaji ayah gak seberapa?”
”Yee, kalo gitu ngapa beli anthurium terus. Kemaren aja Anni minta uang untuk bayar komite gak dikasih, ngomongnya untuk beli anthurium. Untuk apaan sih Yah sebenernya? Yang kemaren aja belum keuurus.”
”Ini juga kan nanti untuk kamu. Kalo laku bisa dapet ratusan juta.”
Itu lagi, itu lagi. Anni benar-benar bosan bosan dengan ayahnya. ”Mana buktinya kalau Ayah mau menjual anthurium? Yang paling besar aja masih ayah simpen.” bantah Anni kesal.
”Sekarang harganya masih rendah. Nanti kalau sudah naik aja jualnya. Ya?” kata ayahnya mencoba memberi solusi.
Anni hanya mengangguk bosan, lalu bergegas pergi ke kamarnya. Tak ada gunanya bicara dengan ayah, batinnya.
Anni membanting tubuhnya di atas tempat tidur. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Ayahnya. Sejak ditinggal ibu Anni, wajah Ayah jadi semakin terlihat tua. Apalagi setelah memelihara anthurium, matanya terlihat sayu gara-gara sering begadang menunggu anthurium-anthuriumnya. Giginya pun semakin menguning lantaran di setiap begadang ayahnya bisa menghabiskan sebungkus rokok atau lebih. Gajinya lebih sering dipakai untuk membeli anthurium daripada ditabung untuk masa tuanya, uang sekolahnya pun sering terbengkalai gara-gara anthurium. Hhhh...ayahnya benar-benar sudah kecanduan anthurium. Benar-benar tak bisa meninggalkannya. Ia tak mau jika nanti ayahnya seperti Qarun yang begitu mencintai hartanya. Ia tak mau jika nanti ayahnya meninggal sambil memeluk anthuriumnya. Ia tak mau, tapi juga tak tahu bagaimana caranya untuk mengingatkan ayahnya. Dan Anni benar-benar tidur dalam segala kepusingannya tentang ayahnya.
Ayam jantan belum lagi berkokok, apalagi matahari, belum tampak dari tempat persemayamannya. Tapi pagi itu Anni bergegas bangun begitu mendengar teriakan ayahnya.
”Anthuriumku! Anthuriumku! Sopo iki sing wan jukuk anthuriumku?”
”Astaghfirullah. Kenapa Yah?”
”Anthurium, anthurium! Anthuriumku ilang siji!” teriak ayahnya seperti kesetanan.
Anni terdiam. Anthurium itu ada di dalam kamarnya, tapi dengan keadaan tanpa daun. Ia baru sadar jika ayahnya begitu menghitung anthurium kepunyaannya.
”Yah, sudahlah. Relakan saja. Kan masih banyak anthurium yang lain.” hibur Anni.
”Tapi yang hilang itu ukurannya besar Ni. Mana ayah rela? Ayah rugi ratusan juta!”
Anni kembali terdiam. Tanpa sadar ia telah membuat investasi ayahnya hilang. Tapi ia belum siap mengatakan yang sejujurnya pada ayahnya. Diam-diam ada sesal yang merasuk ke batin Anni.
Sementara itu ayahnya masih saja berkeliling di teras belakang sambil menghisap kreteknya. Tapi sejurus kemudian ia membuang rokor tersebut ke tanah lalu meremasnya dengan tanah. Lalu ia masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Anni masih juga belum beranjak dari tempatnya berdiri. Tapi kemudian ia ingat bahwa azan subuh sudah memanggil.
Matahari siang ini benar-benar terik bersinar. Anni mengipas-ngipaskan buku tulisnya ke arah muka. Panas yang begitu menyiksa. Ditambah si supir angkot yang terus menambah jumlah penumpang meski tempat duduk seluruhnya telah terisi penuh. Perutnya pun terus bernyanyi minta diisi. Anni mendesah, uang sakunya memang hanya cukup untuk transportasi. Apalagi sarapan tadi sudah tak bersisa lagi, jadilah ia harus memasak dulu untuk bisa memenuhi permintaan dari perutnya. Klakson-klakson yang memenuhi jalanan siang itu makin membuat Anna mengipaskan buku lebih kencang.
Sampai di rumah, Anni membuka kulkas. Telur, sayur kangkung, dan ikan mas tergeletak di situ. Anni kemudian menutup pintu kulkas. Bayangan kelezatan daun anthurium masih juga melekat di lidahnya. Lalu ia berjalan menuju teras belakang sambil mencari-cari anthurium yang berukuran agak kecil. Dia bukannya tak sadar kalau itu tanaman mahal, karenanya ia mencari yang agak kecil. Biar kalau ayahnya sadar anthuriumnya hilang lagi, tak terlalu banyak kerugian yang akan ditanggunggnya. Anni tertawa kecil, kerasukan apa dirinya ini, sampai tega memotong anthurium kesayangan ayahnya hanya untuk urusan perut. Dia sudah tahu kalau dirinya salah melakukan itu, tapi ia memang sudah kerasukan kelezatan anthurium. Tanpa ragu lagi ia segera mengambil pisau dan memotong daun anthurium yang dirasanya cukup kecil. Lalu memasak dan memakannya, juga tanpa ragu-ragu.
”Lo Ni, kok masak ini lagi, kan sudah ayah beliin ikan mas?” tanya ayahnya ketika ia menyodorkan menu yang sama seperti kemarin.
”Emm...Anni bener-bener suka Yah sama sayur ini. Jadi deh, tadi Anni beli ini di warung Mbak surti.” lagi-lagi Anni berkata bohong.
”Jadi udah tau namanya?” tanya Ayahnya lagi.
”Hah?” Anni bingung, ia belum memikirkan nama untuk sayur anthurium ini. ”Emm...namanya sayur kujang Yah. Katanya Mbak Surti gitu?” jawab Anni asal, ia katakan saja apa yang ada di pikirannya.
”Kujang? Kok namanya aneh gitu sih? Tapi besok-besok diabisin dulu apa yang ada di kulkas. Kan sayang kalo busuk.”
Dan Anni hanya mengangguk sambil nyengir.
”Tadi......gak ada orang mencurigakan yang masuk ke rumah kita dan ngambil anthurium kan?”
”Gak ada kok Yah. Lagian juga kalo Ayah pingin aman sewa aja satpam, kalo perlu kasih alarm pengaman aja tu pager.” cerocos Anni.
”Memangnya gaji Ayah berapa?” tanya Ayahnya.
Ah ayah ini, jika merasa tak mampu menjaga anthuriumnya kenapa harus membeli anthurium sebanyak itu. ”Makannya, jangan banyak-banyak dong anthuriumnya. Kan jaganya susah Yah. Kalo Ayah sadar gak bisa ngejaga anthuriumnya, ngapain harus beli sebanyak itu? Kan Cuma nambah susah Ayah.” Ayahnya hanya diam dinasihati begitu dan melanjutkan makannya. Anni bergegas ke belakang untuk mencuci piring kotor. Selalu ada jurang saat kami membicarakan anthurium, tak pernah ada kesepakatan, pikir Anni.
”Anthuriumku! Anthuriumku! Sopo meneh iki sing wani jukuk anthuriumku?” teriakan ayah Anni kembali menggema dini hari itu. Menggantikan suara kokok ayam jantan. Anni menggeliat sebentar di atas tempat tidurnya. Ia sudah tahu kalau ayahnya akan berteriak lagi pagi ini. Ayahnya memang tak terlalu menjaga anthurium yang ada di teras belakang, tapi jika ada yang hilang, pasti akan ada teriakan.
Tapi pagi ini, tak hanya Anni yang bergegas menuju ke teras belakang. Para tetangga pun berdatangan menuju rumah mereka. Heran karena ada teriakan seseorang di pagi buta begini. Melihat banyak tetangga yang menuju teras belakangnya, teriakan ayahnya semakin keras.
”Hayo, sopo iki sing jukuk anthuriumku? Sopo?”
Dituduh begitu, para tetangga langsung merasa tak enak hati. Lalu mereka yang memang tak bersalah itu bergegas perg karena tak mau disalahkan lagi.
”Hee....kok malah lungo? Sini kowe!” teriak ayahnya makin kesetanan. Anni bergegas menuju ke ayahnya.
”Sudahlah ayah. Mereka pergi karena ngerasa gak ngambil anthurium ayah.”
”Enak aja. Siapa yang bisa njamin?” bantah ayahnya.
Mulut Anni langsung terkatup, diam. Ia memang tidak punya bukti apa-apa, tapi ia tentu yakin bahwa para tetangga itu tak mengambil anthurium ayahnya. Karena ia sendirilah yang mengambil anthurium ayahnya untuk dibuat tumisan. Tapi kemudian ayahnya terdiam dan duduk di depan pintu. Wajahnya menampakkan rasa kehilangan yang sangat. Dua anthuriumnya hilang dua hari berturut-turut, dan dia tidak mampu berbuat apa-apa.
”Sudahlah Ayah. Ayah belum shalat subuh kan? Bentar lagi iqamat yah?” ujar Anni mengingatkan ayahnya.
Tapi ayahnya hanya melirik Anni sebentar lalu tetap terdiam. Anni yang merasa bersalah lalu pergi meninggalkan ayahnya. Sungguh dirinya ingin mengingatkan ayahnya bahwa anthurium-anthurium tersebut telah menjadi thagut bagi ayahnya. Sejak memiliki anthurium, ayahnya mulai sering mengundur waktu shalat, mengerjakannya pun lebih banyak di rumah, bukan di masjid yang menjadi keutamaan bagi laki-laki. Tapi begitu mengingat dirinyalah yang mengambil anthurium itu, ditambah dengan melihat wajah ayahnya yang begitu kusut, dirinya semakin tak berdaya. Mulutnya seakan tak bisa berkata apa-apa pada ayahnya.
Namun rupanya kelezatan anthurium masih saja merasuki Anni. Ia masih saja memangkas anthurium milik ayahnya untuk dibuat tumisan. Ia sadar bahwa ayahnya akan berteriak kesetanan pada pagi harinya. Tapi rasa anthurium itu begitu menggodanya, disamping ayahnya yang juga menyukai anthurium itu. Dan kamarnya pun semakin penuh dengan anthurium-anthurium gundul.
Puncaknya, saat kehilangan anthurium yanng ke-10, ayah Anni jatuh sakit. Dalam sakitnya, selalu mengigagu tentang anthuriumnya yang hilang. Juga gigauan tentang istrinya. Wajahnya pasrah, dan matanya selalu menerawang ke langit-langit kamar.
Anni tahu, akhirnya saat ini datang juga. Ia sadar bahwa inilah resikonya jika ia terus-teusan mengambil anthurim daun untuk ditumis. Tapi melihat wajah Ayahnya yang kini terlihat pasrah, Anni merasa bahwa ini saatnya ia jujur pada ayahnya tentang sayur ”kujang” tersebut dan menghentikan kebiasaannya memangkas daun anthurium.
”Yah.” kata Anni saat ayahnya selesai meminum obat yang diberikan dokter.
Ayahnya menoleh dan berkata, ”Ada apa, nak?”
Anni terdiam sejenak, memikirkan kata-kata yang tepat agar ayahnya tak langsung terkejut mendengar apa yang dikatakannya. ”Yah, sebenarnya tumisan sayur kujang yang ayah suka itu diambil dari anthurium milik ayah.”
”Apa? Jadi selama ini kamu yang mengambil anthurium milik ayah, nak?”
Anni mengangguk. ”Waktu itu Anni nyoba untuk pengemis yang kelaperan. Dan jadinya keterusan sampe sekarang. Tapi Yah, disamping itu Anni juga pingin biar Ayah tidak terus-terusan mikirin anthurium. Anthurium itu udah jadi thagut buat ayah. Ayah bahkan rela ngelupain shalat gara-gara ngurusin anthurium itu. Anni gak pingin Ayah ntar jadi kayak Qarun.”
”Tapi justru dengan itu kamu buat Ayah semakin memikirkan anthurium itu. Semalam suntuk ayah mikirin tu anthurium. Apa kamu memang berniat menjadikan ayah sakit seperti ini gara-gara anthurium?”
”Anni sadar kalo ternyata cara Anni salah buat ngingetin Ayah salah. Tapi.......” Anni tak mampu lagi menyelesaikan kalimatnya. Tak disadarinya bulir-bulir bening menetes dari matanya.
”Sudahlah, ayah juga tahu ayah salah. Sampai melupakan Allah dan kamu hanya demi anthurium. Mungkin kalau ibumu masih hidup, ia juga akan menangis sepertimu. Maafkan ayah, nak?”
Tanpa berkata-kata lagi, Anni memeluk ayahnya. Air matanya mengalir semakin deras. Ia tahu ia sangat menyayangi ayahnya, dan bersyukur karena Allah telah mau menyadarkan ayahnya dan dirinya.
”Maafin Anni jgua yah. Anni udah buat ayah rugi ratusan juta.”
Dan ayahnya hanya mengangguk lalu berkata, ”Tapi anthurium memang benar-benar enak, kamu mau kan masakin lagi untuk Ayah?”
Anni menatap ayahnya heran, ”Ayah gak ngerasa rugi?” tanyanya
Dan hanya senyum yang menjawab pertanyaan Anni, yang membuat Anni tersenyum untuk kemudian mengangguk.
Wanna More.?
”Dia sudah seperti pengganti ibumu, Ni.” kata ayahnya saat Anni menanyakan alasan kenapa ayahnya begitu menyukai anthurium.
Anni terdiam. Ibunya memang sudah tiada sejak 6 tahun yang lalu. ”Iya, tapi apa dulu ibu menyukai tanaman ini? Kenapa aya bisa bilang begitu? Kenapa juga ayah rela menukar tanaman-tanaman ini dengan uang tabungan yang sudah ayah kumpulkan bertahun-tahun?” bantahnya.
”Yah, begitulah kalau sudah cinta, Ni.” jawab ayahnya sambil melanjutkan pekerjaannya menanam bibit anthurium yang baru ke dalam pot. Suatu jawaban yang makin membuat kening Anni berkerut karena heran dan bingung.
Lalu mata Anni bergerak ke arah pintu gerbang yang setengah terbuka. Seorang pengemis cilik menatap ke arahnya. Agaknya ia ingin mengemis padanya, namun urung karena dirinya termangu terus sejak tadi. Rasa ibanya muncul, perasaannya memang mudah tersentuh jika melihat pengemis atau gelandangan. Anni berjalan ke arah pengemis itu. Bajunya sudah banyak yang berlubang di beberapa bagian. Mukanya dekil kecoklatan, pertanda bahwa ia sudah bekerja keras sejak pagi.
Anni merogoh kantongnya. Kosong. Ia ingat bahwa uang sakunya telah ia habiskan untuk ongkos angkotnya ke sekolah. ia menatap pengemis itu sekali lagi. Dia sedang memegangi perutnya, ingin menunjukkan bahwa ia lapar.
”Dek, mbak gak punya uang nih. Gimana kalo adek mbak kasih makan aja? Yah?” Pengemis itu mengangguk, tak bisa menolak karena memang perutnya sudah minta diisi sejak pagi tadi. Ia mengikuti saja langkah Anni yang mengajaknya masuk ke dalam rumah.
”Dek, adek duduk di sini dulu ya. Mbak mau ngambilin makanannya.” dan sekali lagi Anni hanya melihat anggukan dari pengemis kecil itu.
Anni bergegas menuju ruang makan dan membuka tudung saji di atas meja. Hanya ada piring kosong bekas tempat menaruh telur ceplok yang ia masak siang tadi. Lalu tangannya bergerak membuka pintu kulkas, ia mengeluh, hanya ada cabai, bawang, dan bumbu-bumbu lain.
”Aduh, masak apaan nih? Masak mau ngasih bumbu sama adek itu?” pikirnya bingung. Tak mungkin ia berkata kepada pengemis itu bahwan di rumahnya tidak ada makanan. Kalaupun bisa setidaknya ia memberikan sedikit uang, tapi sayangnya tak sepeser pun uang digenggamnya saat ini.
Anni berjalan menuju teras belakang. Ekor matanya menangkap beberapa Anthurium yang sengaja ditaruh ayahnya di situ. Tiba-tiba pikirannya terbuka. Ia ingat sebuah berita di koran kemarin bahwa ada seorang ibu yang menjadikan Anthurium sebagai lalapan, yang membuat suaminya langsung terserang stroke. Mungkin anthurium ini juga enak jika ditumis, pikirnya.
Anni mengambil pisau untuk memotong anthurium. Tapi kemudian ia berhenti, jangan-jangan ayahnya nanti akan terserang stroke juga, tapi nggak papa deh, ayah kan punya penyakit stroke. Lalu dengan cepat Anni memotong anthurium itu dan menumisnya. Anni mengambil nasi dan tumisan itu lalu dibawanya ke ruang tamu.
”Dek, maaf ya menunggu la....” kalimatnya tak sempat terselesaikat kala melihat wujud si pengemis sudah tak ada lagi di tempatnya. Ia lupa mengingatkan pengemis itu bahwa dirinya akan memasak dulu. Anni terduduk lemas, satu pahalan untuknya melayang hari ini. Tanpa sadar ia memakan makanan yang disiapkan untuk pengemis itu.
”Enak. Gak nyangka tanaman sekelas anthurium enak juga dibuat tumisan.” dan ia terus melahap makanan tersebut hingga piringnya licin tandas.
Dan malamnya, ia pun menghidangkan tumisan anthurium tersebut pada ayahnya.
”Gimana yah, enak gak?” tanya Anni sambil tersenyum.
”Enak kok. Sayur apa nih namanya?” ayahnya balik bertanya.
Senyum Anni langsung lenyap. Namanya? Tidak terpikir dalam otaknya jika ayahnya akan menanyakan hal tersebut. Tidak mungkin ia menyebut anthurium, bisa-bisa ayahnya langsung naik darah.
”Emm...dak tau yah. Tadi Anni asal ambil aja di warungnya Mbak Surti. Gak sempet nanya namanya.” jawab Anni asal.
”Oh.”
”Yah, boleh gak Anni minta tambahan uang saku. Anni sering kelaparan Yah, gak ada uang untuk beli makanan. Masak Cuma cukup buat bayar angkot pulang pergi?”
”Wah, gak bisa Ni. Rencananya nanti ayah mau beli bibit anthurium lagi. Kamu kan tahu kalo gaji ayah gak seberapa?”
”Yee, kalo gitu ngapa beli anthurium terus. Kemaren aja Anni minta uang untuk bayar komite gak dikasih, ngomongnya untuk beli anthurium. Untuk apaan sih Yah sebenernya? Yang kemaren aja belum keuurus.”
”Ini juga kan nanti untuk kamu. Kalo laku bisa dapet ratusan juta.”
Itu lagi, itu lagi. Anni benar-benar bosan bosan dengan ayahnya. ”Mana buktinya kalau Ayah mau menjual anthurium? Yang paling besar aja masih ayah simpen.” bantah Anni kesal.
”Sekarang harganya masih rendah. Nanti kalau sudah naik aja jualnya. Ya?” kata ayahnya mencoba memberi solusi.
Anni hanya mengangguk bosan, lalu bergegas pergi ke kamarnya. Tak ada gunanya bicara dengan ayah, batinnya.
Anni membanting tubuhnya di atas tempat tidur. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Ayahnya. Sejak ditinggal ibu Anni, wajah Ayah jadi semakin terlihat tua. Apalagi setelah memelihara anthurium, matanya terlihat sayu gara-gara sering begadang menunggu anthurium-anthuriumnya. Giginya pun semakin menguning lantaran di setiap begadang ayahnya bisa menghabiskan sebungkus rokok atau lebih. Gajinya lebih sering dipakai untuk membeli anthurium daripada ditabung untuk masa tuanya, uang sekolahnya pun sering terbengkalai gara-gara anthurium. Hhhh...ayahnya benar-benar sudah kecanduan anthurium. Benar-benar tak bisa meninggalkannya. Ia tak mau jika nanti ayahnya seperti Qarun yang begitu mencintai hartanya. Ia tak mau jika nanti ayahnya meninggal sambil memeluk anthuriumnya. Ia tak mau, tapi juga tak tahu bagaimana caranya untuk mengingatkan ayahnya. Dan Anni benar-benar tidur dalam segala kepusingannya tentang ayahnya.
Ayam jantan belum lagi berkokok, apalagi matahari, belum tampak dari tempat persemayamannya. Tapi pagi itu Anni bergegas bangun begitu mendengar teriakan ayahnya.
”Anthuriumku! Anthuriumku! Sopo iki sing wan jukuk anthuriumku?”
”Astaghfirullah. Kenapa Yah?”
”Anthurium, anthurium! Anthuriumku ilang siji!” teriak ayahnya seperti kesetanan.
Anni terdiam. Anthurium itu ada di dalam kamarnya, tapi dengan keadaan tanpa daun. Ia baru sadar jika ayahnya begitu menghitung anthurium kepunyaannya.
”Yah, sudahlah. Relakan saja. Kan masih banyak anthurium yang lain.” hibur Anni.
”Tapi yang hilang itu ukurannya besar Ni. Mana ayah rela? Ayah rugi ratusan juta!”
Anni kembali terdiam. Tanpa sadar ia telah membuat investasi ayahnya hilang. Tapi ia belum siap mengatakan yang sejujurnya pada ayahnya. Diam-diam ada sesal yang merasuk ke batin Anni.
Sementara itu ayahnya masih saja berkeliling di teras belakang sambil menghisap kreteknya. Tapi sejurus kemudian ia membuang rokor tersebut ke tanah lalu meremasnya dengan tanah. Lalu ia masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Anni masih juga belum beranjak dari tempatnya berdiri. Tapi kemudian ia ingat bahwa azan subuh sudah memanggil.
Matahari siang ini benar-benar terik bersinar. Anni mengipas-ngipaskan buku tulisnya ke arah muka. Panas yang begitu menyiksa. Ditambah si supir angkot yang terus menambah jumlah penumpang meski tempat duduk seluruhnya telah terisi penuh. Perutnya pun terus bernyanyi minta diisi. Anni mendesah, uang sakunya memang hanya cukup untuk transportasi. Apalagi sarapan tadi sudah tak bersisa lagi, jadilah ia harus memasak dulu untuk bisa memenuhi permintaan dari perutnya. Klakson-klakson yang memenuhi jalanan siang itu makin membuat Anna mengipaskan buku lebih kencang.
Sampai di rumah, Anni membuka kulkas. Telur, sayur kangkung, dan ikan mas tergeletak di situ. Anni kemudian menutup pintu kulkas. Bayangan kelezatan daun anthurium masih juga melekat di lidahnya. Lalu ia berjalan menuju teras belakang sambil mencari-cari anthurium yang berukuran agak kecil. Dia bukannya tak sadar kalau itu tanaman mahal, karenanya ia mencari yang agak kecil. Biar kalau ayahnya sadar anthuriumnya hilang lagi, tak terlalu banyak kerugian yang akan ditanggunggnya. Anni tertawa kecil, kerasukan apa dirinya ini, sampai tega memotong anthurium kesayangan ayahnya hanya untuk urusan perut. Dia sudah tahu kalau dirinya salah melakukan itu, tapi ia memang sudah kerasukan kelezatan anthurium. Tanpa ragu lagi ia segera mengambil pisau dan memotong daun anthurium yang dirasanya cukup kecil. Lalu memasak dan memakannya, juga tanpa ragu-ragu.
”Lo Ni, kok masak ini lagi, kan sudah ayah beliin ikan mas?” tanya ayahnya ketika ia menyodorkan menu yang sama seperti kemarin.
”Emm...Anni bener-bener suka Yah sama sayur ini. Jadi deh, tadi Anni beli ini di warung Mbak surti.” lagi-lagi Anni berkata bohong.
”Jadi udah tau namanya?” tanya Ayahnya lagi.
”Hah?” Anni bingung, ia belum memikirkan nama untuk sayur anthurium ini. ”Emm...namanya sayur kujang Yah. Katanya Mbak Surti gitu?” jawab Anni asal, ia katakan saja apa yang ada di pikirannya.
”Kujang? Kok namanya aneh gitu sih? Tapi besok-besok diabisin dulu apa yang ada di kulkas. Kan sayang kalo busuk.”
Dan Anni hanya mengangguk sambil nyengir.
”Tadi......gak ada orang mencurigakan yang masuk ke rumah kita dan ngambil anthurium kan?”
”Gak ada kok Yah. Lagian juga kalo Ayah pingin aman sewa aja satpam, kalo perlu kasih alarm pengaman aja tu pager.” cerocos Anni.
”Memangnya gaji Ayah berapa?” tanya Ayahnya.
Ah ayah ini, jika merasa tak mampu menjaga anthuriumnya kenapa harus membeli anthurium sebanyak itu. ”Makannya, jangan banyak-banyak dong anthuriumnya. Kan jaganya susah Yah. Kalo Ayah sadar gak bisa ngejaga anthuriumnya, ngapain harus beli sebanyak itu? Kan Cuma nambah susah Ayah.” Ayahnya hanya diam dinasihati begitu dan melanjutkan makannya. Anni bergegas ke belakang untuk mencuci piring kotor. Selalu ada jurang saat kami membicarakan anthurium, tak pernah ada kesepakatan, pikir Anni.
”Anthuriumku! Anthuriumku! Sopo meneh iki sing wani jukuk anthuriumku?” teriakan ayah Anni kembali menggema dini hari itu. Menggantikan suara kokok ayam jantan. Anni menggeliat sebentar di atas tempat tidurnya. Ia sudah tahu kalau ayahnya akan berteriak lagi pagi ini. Ayahnya memang tak terlalu menjaga anthurium yang ada di teras belakang, tapi jika ada yang hilang, pasti akan ada teriakan.
Tapi pagi ini, tak hanya Anni yang bergegas menuju ke teras belakang. Para tetangga pun berdatangan menuju rumah mereka. Heran karena ada teriakan seseorang di pagi buta begini. Melihat banyak tetangga yang menuju teras belakangnya, teriakan ayahnya semakin keras.
”Hayo, sopo iki sing jukuk anthuriumku? Sopo?”
Dituduh begitu, para tetangga langsung merasa tak enak hati. Lalu mereka yang memang tak bersalah itu bergegas perg karena tak mau disalahkan lagi.
”Hee....kok malah lungo? Sini kowe!” teriak ayahnya makin kesetanan. Anni bergegas menuju ke ayahnya.
”Sudahlah ayah. Mereka pergi karena ngerasa gak ngambil anthurium ayah.”
”Enak aja. Siapa yang bisa njamin?” bantah ayahnya.
Mulut Anni langsung terkatup, diam. Ia memang tidak punya bukti apa-apa, tapi ia tentu yakin bahwa para tetangga itu tak mengambil anthurium ayahnya. Karena ia sendirilah yang mengambil anthurium ayahnya untuk dibuat tumisan. Tapi kemudian ayahnya terdiam dan duduk di depan pintu. Wajahnya menampakkan rasa kehilangan yang sangat. Dua anthuriumnya hilang dua hari berturut-turut, dan dia tidak mampu berbuat apa-apa.
”Sudahlah Ayah. Ayah belum shalat subuh kan? Bentar lagi iqamat yah?” ujar Anni mengingatkan ayahnya.
Tapi ayahnya hanya melirik Anni sebentar lalu tetap terdiam. Anni yang merasa bersalah lalu pergi meninggalkan ayahnya. Sungguh dirinya ingin mengingatkan ayahnya bahwa anthurium-anthurium tersebut telah menjadi thagut bagi ayahnya. Sejak memiliki anthurium, ayahnya mulai sering mengundur waktu shalat, mengerjakannya pun lebih banyak di rumah, bukan di masjid yang menjadi keutamaan bagi laki-laki. Tapi begitu mengingat dirinyalah yang mengambil anthurium itu, ditambah dengan melihat wajah ayahnya yang begitu kusut, dirinya semakin tak berdaya. Mulutnya seakan tak bisa berkata apa-apa pada ayahnya.
Namun rupanya kelezatan anthurium masih saja merasuki Anni. Ia masih saja memangkas anthurium milik ayahnya untuk dibuat tumisan. Ia sadar bahwa ayahnya akan berteriak kesetanan pada pagi harinya. Tapi rasa anthurium itu begitu menggodanya, disamping ayahnya yang juga menyukai anthurium itu. Dan kamarnya pun semakin penuh dengan anthurium-anthurium gundul.
Puncaknya, saat kehilangan anthurium yanng ke-10, ayah Anni jatuh sakit. Dalam sakitnya, selalu mengigagu tentang anthuriumnya yang hilang. Juga gigauan tentang istrinya. Wajahnya pasrah, dan matanya selalu menerawang ke langit-langit kamar.
Anni tahu, akhirnya saat ini datang juga. Ia sadar bahwa inilah resikonya jika ia terus-teusan mengambil anthurim daun untuk ditumis. Tapi melihat wajah Ayahnya yang kini terlihat pasrah, Anni merasa bahwa ini saatnya ia jujur pada ayahnya tentang sayur ”kujang” tersebut dan menghentikan kebiasaannya memangkas daun anthurium.
”Yah.” kata Anni saat ayahnya selesai meminum obat yang diberikan dokter.
Ayahnya menoleh dan berkata, ”Ada apa, nak?”
Anni terdiam sejenak, memikirkan kata-kata yang tepat agar ayahnya tak langsung terkejut mendengar apa yang dikatakannya. ”Yah, sebenarnya tumisan sayur kujang yang ayah suka itu diambil dari anthurium milik ayah.”
”Apa? Jadi selama ini kamu yang mengambil anthurium milik ayah, nak?”
Anni mengangguk. ”Waktu itu Anni nyoba untuk pengemis yang kelaperan. Dan jadinya keterusan sampe sekarang. Tapi Yah, disamping itu Anni juga pingin biar Ayah tidak terus-terusan mikirin anthurium. Anthurium itu udah jadi thagut buat ayah. Ayah bahkan rela ngelupain shalat gara-gara ngurusin anthurium itu. Anni gak pingin Ayah ntar jadi kayak Qarun.”
”Tapi justru dengan itu kamu buat Ayah semakin memikirkan anthurium itu. Semalam suntuk ayah mikirin tu anthurium. Apa kamu memang berniat menjadikan ayah sakit seperti ini gara-gara anthurium?”
”Anni sadar kalo ternyata cara Anni salah buat ngingetin Ayah salah. Tapi.......” Anni tak mampu lagi menyelesaikan kalimatnya. Tak disadarinya bulir-bulir bening menetes dari matanya.
”Sudahlah, ayah juga tahu ayah salah. Sampai melupakan Allah dan kamu hanya demi anthurium. Mungkin kalau ibumu masih hidup, ia juga akan menangis sepertimu. Maafkan ayah, nak?”
Tanpa berkata-kata lagi, Anni memeluk ayahnya. Air matanya mengalir semakin deras. Ia tahu ia sangat menyayangi ayahnya, dan bersyukur karena Allah telah mau menyadarkan ayahnya dan dirinya.
”Maafin Anni jgua yah. Anni udah buat ayah rugi ratusan juta.”
Dan ayahnya hanya mengangguk lalu berkata, ”Tapi anthurium memang benar-benar enak, kamu mau kan masakin lagi untuk Ayah?”
Anni menatap ayahnya heran, ”Ayah gak ngerasa rugi?” tanyanya
Dan hanya senyum yang menjawab pertanyaan Anni, yang membuat Anni tersenyum untuk kemudian mengangguk.
"Andai Cinta Tahu"
Senyum itu, sungguh manis dengan bibir manis dan indah. Juga dengan mata sipit yang nyaris tertelan senyum itu. Manis, dan menimbulkan sensasi lain……….
Dan cinta pun mengalir begitu saja, deras menghujani batin Arini. Untuk pertama kalinya Arini tak bisa melupakan bibir seseorang, begitu manis, begitu indah. Bibir seseorang yang mampu menjalin senyum terindah yang pernah Arini lihat. Dan karena bibir itu, untuk pertama kalinya Arini………..jatuh cinta.
Minggu pagi, 24 Desember 2006
“Apa? Rapat Rohis? Kok mendadak?” Tanya Arini langsung bercucuran saat Neti meneleponnya.
“Iya, untuk tahun depan. Program-program kita setengah tahun ini banyak yang kurang berhasil. Ntar kita evaluasi plus nyari trik biar adik kelas yang ikut program Rohis makin banyak. Ntar ada Mbak Ani yang bimbing kok. Gak keberatan kan?”
Arini terdiam. Ia tak keberatan, karena memang sudah resiko jika menjadi ketua Divisi Keakhwatan. Ia juga tahu, bahwa ini panggilan dakwah yang tak boleh diabaikan.
“Gak kok? Insya Allah aku datang. Jam berapa?” Tanya Arini lagi sambil melihat jam dinding, jam ½ 6.
“Ok. Jam 8 di masjid Ar-Rahman seperti biasa”
Dan klik. Telepon pun terputus..
Arini segera beranjak menuju kamar mandi. Tubuhnya masih lelah akibat mengetikkan makalah ayahnya. Hah……….tapi ia tahu dakwah sudah memanggilnya.
Pagi masih terasa saat Arini keluar rumah. Ia melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 7 lebih. Sengaja ia berangkat lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena ingin menikmati pagi.
Arini berjalan lambat, sekali lagi hanya untuk menikmati pagi. Tak sengaja bola matanya bergerak ke sebuah rumah bertingkat di sisi kanan jalan. Ia berhenti. Apa si pemilik rumah belum mau nempatin rumahnya ya? Seingatnya sudah setahun semenjak rumah ini selesai dibangun, masih saja sepi. Apa si empunya tidak takut kalau nantinya jin akan menghuni rumahnya, pikir Arini, heran. Matanya menerawang ke arah jalan, namun masih belum beranjak.
“Pagi, mbak. Kok diem aja di depan rumah saya?” sebuah suara tiba-tiba menggetarkan gendang telinga Arini. Arini menoleh, sadar bahwa dirinya sedang mematung di depan rumah itu. Si pemilik suara tersenyum manis, semanis……..bibirnya! Arini pun tersipu dan berkata, “Oh, maaf. Saya hanya lewat, kok. Maaf kalau mengganggu.”
Dan pemilik suara itu kembali tersenyum manis, semanis bibirnya. Mata sipitnya seakan tenggelam. Arini pun tersipu malu, menggangguk, lalu beranjak pergi.
Seakan melayang Arini berjalan menuju tempat pemberhentian angkot. Dia……begitu manis. Apalagi bibirnya, manis dan indah. Juga mata sipitnya, mengingatkannya pada sosok Choi Min-hwan, artis Korea yang dulu sempat digandrunginya semasa SMP. Bibir Choi Min-hwan juga begitu manis. Mereka….sungguh mirip.
Saat berada di angkot pun, Arini seperti merasa berada di dalam pesawat. Tubuhnya terasa begitu ringan. Sampai pada saat rapat pun, tak ada yang bisa dilakukan Arini, kecuali….diam bertopang dagu. Rapat hari itu selesai memang, tapi tanpa satu pun masukan dar sang ketua Divisi Akhwat. Hal yang membuat heran para pengurus Rohis yang lain.
Lalu cerita ini mengalir………
Minggu malam, pada tanggal yang sama di dalam buku harian Arini
Ya rabb, untuk pertama kali ku tak bisa melupakan bibir seseorang. Ya, bibir! Bibir itu begitu manis, begitu indah, dan mampu merangkai satu senyuman terindah. Sungguh manis, dan indah.
Ya Rabb, bahkan suaranya pun tak bisa kulupakan. Begitu singkat, namun merdu. Terlalu manis.
“Dan ketika cinta itu datang
hidup ini mengalir….
begitu saja
sampai ia menemukan tempat muaranya………..
dan ketika cinta itu menyapa
hidup ini terasa ringan……….
terbang ke mana saja ia mau
sampai angin enggan menerbangkannya lagi………
dan cinta itu,
cinta itulah yang selalu mengisi bayangan dalam bola mata
memenuhi ruang hampa dalam telinga
dan juga….
mengisi relung hati”
Berikutnya, tak banyak perubahan dalam diri Arini, selain selalu mengingat-ingat bentuk bibir manis dan indah itu. Selain Arini yang setiap pagi berhenti sejenak di depan rumah bertingkat itu, sekedar menunggu sapaan dan senyuman yang tak dinyana tiap pagi selalu datang untuknya, dan sikapnya yang tak jua berubah menghadapi itu. Tersipu, lalu beranjak pergi. Kegiatannya di Rohis pun tak terlalu banyak terpengaruh. Karena ia tahu bahwa cinta ini harus dijaga. Rapat dalam relung hati.
Sabtu malam, 31 Desember 2006 di dalam buku harian Arini
Ya Rabb, ku tak tahu in sebenarnya rasa apa?
Kadang ku senang karena diliputi rasa ini,
Tapi, ku juga takut
Entah kenapa, mungkin ku takut ternoda
Ya Rabb, walau hanya sapaan dan senyuman di pagi hari, namun itulah yang membuatku didera rasa rindu. Walau setiap hari tersedia untuk ku. Dan maafkan aku karena hanya melihat dari fisiknya. Karena ku benar-benar menyukai bibirnya, dan juga jatuh cinta padanya.
Bulan-bulan pun berlalu, melewati pergantian tahun………..
Masih juga tak banyak yang berubah dari sosok Arini, selain dirinya yang sudah bisa membalas senyuman si pemilik bibir manis. Amanahnya di Rohis, sekali lagi masih tak terpengaruh oleh rasa itu yang begitu baik dijaganya. Shalat malam, tilawah, hafalan, liqa’ masih dijalankannya. Memang tak banyak yang berubah, selain waktu luang yang tak pernah absen terisi oleh wajah si pemilik bibir indah.
Dan lalu, waktu pun masih dan akan terus berlalu…..
“Dan………
hidup ini pun telah sampai pada muaranya
dan………
angin pun tak mau lagi menerbangkan hidup ke mana saja ia suka
karena cinta itu…….
harus segera disadari
karena cinta tak menginginkan,
hidup mengalir dan melayang begitu saja…”
Siang itu, untuk pertama kalinya Arini berhenti di depan rumah bertingkat itu. Dan ia tak perlu menunggu si pemilik bibir manis itu keluar dan menyapa untuknya. Dia sudah di luar seakan tahu kalau Arini siang itu akan berhenti di depan rumahnya, dan tetap memberikan senyuman terindah yang pernah Arini lihat, dengan mata sipit yang nyaris tenggelam.
Dan…….
Arini menunduk. Dalam. Lalu bulir-bulir bening menetes dari kedua kelopak matanya. Ia menangis, menangis untuk pertama kalinya kala menghadapi senyum itu. Ia menangis, karena menyadari suatu hal, yang telah ia pahami sejak dulu.
Arini memandang si pemilik senyum terindah sesaat, tersenyum, menunduk lalu beranjak.
Dan kini………
Perasaan si pemilik bibir manis bicara. Tentang keheranannya akan gadis yang biasanya membalas senyumnya, siang tadi menangis untuk alasan yang tak dimengerti.
“Wahai gadis,
sungguh, senyum ini hanya untukmu
sapaan ini,
yang setiap pagi kuberikan padamu
juga hanya untukmu
dan cinta mulai memenuhi relung hati
seiring waktu……..
tapi, cinta ini akan tetap terjaga
karena aku tahu cinta itu putih bersih”
Dan sang pemilik senyum itu tahu, bahwa ia akan tetap memberi senyum dan sapaan pada gadis itu, yang melewati rumahnya setiap pagi. Dan ia hanya akan memberikan itu, tak lebih. Karena ia hanya ingin cintanya terjaga. Rapat dalam relung hati.
“Bahwa cinta memang bisa membuat segalanya berputar
180 derajat
dan apakah cinta memang tak pernah tahu
bahwa ia bisa membuat tembaga menjadi emas
bahwa ia bisa mengubah segala yang buruk menjadi indah
dan apakah jika ia tahu?
ia akan menangis?
dan takkah ia melihat,
bahwa banyak yang terjebak karenanya
bahwa banyak yang menangis, juga tertawa karenanya
ah,………..
andai cinta tahu……..”
Dan Arini pun menangis malam itu, dalam shalat lail yang dilakoninya. Menangis karena ia telah mulai melupakan cinta sejatinya. Menangis karena ibadah yang dijalaninya kini seakan tanpa ruh. Menangis karena kini ia mulai malas menggapai cinta-Nya. Menangis karena ia begitu mencintai si pemilik bibir indah itu. Menangis karena takut cintanya nanti berada pada tempat yang salah.
Arini terus berharap dalam sujud panjangnya, agar Sang Pemilik Cinta tidak marah padanya. Agar dia masih mau memberikan cinta untuknya. Dan agar cintanya pada si pemilik senyum terindah tetap terjaga, murni.
Dan arini pun terus menangis hingga fajar menyapanya lembut, memberi satu tekad.
Pagi itu datang lagi. Masih dengan mentari yang mulai beranjak tinggi. Masih dengan embun yang mulai mengering. Arini pun menikmati pagi itu, seperti biasa. Namun, sebuah tekad pagi ini mampir di benaknya bahwa ia tak akan berhenti di depan rumah sang pemilik bibir manis, juga tak akan menunggu sapaan dan senyuman untuknya.
Sampai di tempat pemberhentian angkot, Arini tertegun. Si pemilik bibir indah itu telah ada di sana. Dan ia, ketika melihat arini, masih tetap tersenyum dengan mata sipit yang nyaris tertelan oleh senyumannya. Lalu ia memandang ke arah jalan raya yang masih sepi tanpa menunggu Arini membalas senyumannya, tanpa sapaan. Dan Arini, hanya bisa tersenyum dalam hati, lalu berdiri agak jauh dari si pemilik senyum terindah untuk menunggu angkot.
“Ya, dan cinta ini akan ku jaga
tapi, takkan ku menangis jika ia hilang terkikis masa
karna ku tahu,
ku masih punya cinta yang takkan meninggalkanku
yang kan selalu ku kejar dan ku harap
karna sekali lagi,
cinta tak ingin
hidup mengalir dan melayang begitu saja,
tanpa ada arah yang menemani”
ditulis saat menunggu detik-detik
menuju umur 15
Sudah pernah dimuat di blogQ yang satu lagi:
aboutansdromeda.multiply.com (dah gak aktip) Wanna More.?
Dan cinta pun mengalir begitu saja, deras menghujani batin Arini. Untuk pertama kalinya Arini tak bisa melupakan bibir seseorang, begitu manis, begitu indah. Bibir seseorang yang mampu menjalin senyum terindah yang pernah Arini lihat. Dan karena bibir itu, untuk pertama kalinya Arini………..jatuh cinta.
Minggu pagi, 24 Desember 2006
“Apa? Rapat Rohis? Kok mendadak?” Tanya Arini langsung bercucuran saat Neti meneleponnya.
“Iya, untuk tahun depan. Program-program kita setengah tahun ini banyak yang kurang berhasil. Ntar kita evaluasi plus nyari trik biar adik kelas yang ikut program Rohis makin banyak. Ntar ada Mbak Ani yang bimbing kok. Gak keberatan kan?”
Arini terdiam. Ia tak keberatan, karena memang sudah resiko jika menjadi ketua Divisi Keakhwatan. Ia juga tahu, bahwa ini panggilan dakwah yang tak boleh diabaikan.
“Gak kok? Insya Allah aku datang. Jam berapa?” Tanya Arini lagi sambil melihat jam dinding, jam ½ 6.
“Ok. Jam 8 di masjid Ar-Rahman seperti biasa”
Dan klik. Telepon pun terputus..
Arini segera beranjak menuju kamar mandi. Tubuhnya masih lelah akibat mengetikkan makalah ayahnya. Hah……….tapi ia tahu dakwah sudah memanggilnya.
Pagi masih terasa saat Arini keluar rumah. Ia melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 7 lebih. Sengaja ia berangkat lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena ingin menikmati pagi.
Arini berjalan lambat, sekali lagi hanya untuk menikmati pagi. Tak sengaja bola matanya bergerak ke sebuah rumah bertingkat di sisi kanan jalan. Ia berhenti. Apa si pemilik rumah belum mau nempatin rumahnya ya? Seingatnya sudah setahun semenjak rumah ini selesai dibangun, masih saja sepi. Apa si empunya tidak takut kalau nantinya jin akan menghuni rumahnya, pikir Arini, heran. Matanya menerawang ke arah jalan, namun masih belum beranjak.
“Pagi, mbak. Kok diem aja di depan rumah saya?” sebuah suara tiba-tiba menggetarkan gendang telinga Arini. Arini menoleh, sadar bahwa dirinya sedang mematung di depan rumah itu. Si pemilik suara tersenyum manis, semanis……..bibirnya! Arini pun tersipu dan berkata, “Oh, maaf. Saya hanya lewat, kok. Maaf kalau mengganggu.”
Dan pemilik suara itu kembali tersenyum manis, semanis bibirnya. Mata sipitnya seakan tenggelam. Arini pun tersipu malu, menggangguk, lalu beranjak pergi.
Seakan melayang Arini berjalan menuju tempat pemberhentian angkot. Dia……begitu manis. Apalagi bibirnya, manis dan indah. Juga mata sipitnya, mengingatkannya pada sosok Choi Min-hwan, artis Korea yang dulu sempat digandrunginya semasa SMP. Bibir Choi Min-hwan juga begitu manis. Mereka….sungguh mirip.
Saat berada di angkot pun, Arini seperti merasa berada di dalam pesawat. Tubuhnya terasa begitu ringan. Sampai pada saat rapat pun, tak ada yang bisa dilakukan Arini, kecuali….diam bertopang dagu. Rapat hari itu selesai memang, tapi tanpa satu pun masukan dar sang ketua Divisi Akhwat. Hal yang membuat heran para pengurus Rohis yang lain.
Lalu cerita ini mengalir………
Minggu malam, pada tanggal yang sama di dalam buku harian Arini
Ya rabb, untuk pertama kali ku tak bisa melupakan bibir seseorang. Ya, bibir! Bibir itu begitu manis, begitu indah, dan mampu merangkai satu senyuman terindah. Sungguh manis, dan indah.
Ya Rabb, bahkan suaranya pun tak bisa kulupakan. Begitu singkat, namun merdu. Terlalu manis.
“Dan ketika cinta itu datang
hidup ini mengalir….
begitu saja
sampai ia menemukan tempat muaranya………..
dan ketika cinta itu menyapa
hidup ini terasa ringan……….
terbang ke mana saja ia mau
sampai angin enggan menerbangkannya lagi………
dan cinta itu,
cinta itulah yang selalu mengisi bayangan dalam bola mata
memenuhi ruang hampa dalam telinga
dan juga….
mengisi relung hati”
Berikutnya, tak banyak perubahan dalam diri Arini, selain selalu mengingat-ingat bentuk bibir manis dan indah itu. Selain Arini yang setiap pagi berhenti sejenak di depan rumah bertingkat itu, sekedar menunggu sapaan dan senyuman yang tak dinyana tiap pagi selalu datang untuknya, dan sikapnya yang tak jua berubah menghadapi itu. Tersipu, lalu beranjak pergi. Kegiatannya di Rohis pun tak terlalu banyak terpengaruh. Karena ia tahu bahwa cinta ini harus dijaga. Rapat dalam relung hati.
Sabtu malam, 31 Desember 2006 di dalam buku harian Arini
Ya Rabb, ku tak tahu in sebenarnya rasa apa?
Kadang ku senang karena diliputi rasa ini,
Tapi, ku juga takut
Entah kenapa, mungkin ku takut ternoda
Ya Rabb, walau hanya sapaan dan senyuman di pagi hari, namun itulah yang membuatku didera rasa rindu. Walau setiap hari tersedia untuk ku. Dan maafkan aku karena hanya melihat dari fisiknya. Karena ku benar-benar menyukai bibirnya, dan juga jatuh cinta padanya.
Bulan-bulan pun berlalu, melewati pergantian tahun………..
Masih juga tak banyak yang berubah dari sosok Arini, selain dirinya yang sudah bisa membalas senyuman si pemilik bibir manis. Amanahnya di Rohis, sekali lagi masih tak terpengaruh oleh rasa itu yang begitu baik dijaganya. Shalat malam, tilawah, hafalan, liqa’ masih dijalankannya. Memang tak banyak yang berubah, selain waktu luang yang tak pernah absen terisi oleh wajah si pemilik bibir indah.
Dan lalu, waktu pun masih dan akan terus berlalu…..
“Dan………
hidup ini pun telah sampai pada muaranya
dan………
angin pun tak mau lagi menerbangkan hidup ke mana saja ia suka
karena cinta itu…….
harus segera disadari
karena cinta tak menginginkan,
hidup mengalir dan melayang begitu saja…”
Siang itu, untuk pertama kalinya Arini berhenti di depan rumah bertingkat itu. Dan ia tak perlu menunggu si pemilik bibir manis itu keluar dan menyapa untuknya. Dia sudah di luar seakan tahu kalau Arini siang itu akan berhenti di depan rumahnya, dan tetap memberikan senyuman terindah yang pernah Arini lihat, dengan mata sipit yang nyaris tenggelam.
Dan…….
Arini menunduk. Dalam. Lalu bulir-bulir bening menetes dari kedua kelopak matanya. Ia menangis, menangis untuk pertama kalinya kala menghadapi senyum itu. Ia menangis, karena menyadari suatu hal, yang telah ia pahami sejak dulu.
Arini memandang si pemilik senyum terindah sesaat, tersenyum, menunduk lalu beranjak.
Dan kini………
Perasaan si pemilik bibir manis bicara. Tentang keheranannya akan gadis yang biasanya membalas senyumnya, siang tadi menangis untuk alasan yang tak dimengerti.
“Wahai gadis,
sungguh, senyum ini hanya untukmu
sapaan ini,
yang setiap pagi kuberikan padamu
juga hanya untukmu
dan cinta mulai memenuhi relung hati
seiring waktu……..
tapi, cinta ini akan tetap terjaga
karena aku tahu cinta itu putih bersih”
Dan sang pemilik senyum itu tahu, bahwa ia akan tetap memberi senyum dan sapaan pada gadis itu, yang melewati rumahnya setiap pagi. Dan ia hanya akan memberikan itu, tak lebih. Karena ia hanya ingin cintanya terjaga. Rapat dalam relung hati.
“Bahwa cinta memang bisa membuat segalanya berputar
180 derajat
dan apakah cinta memang tak pernah tahu
bahwa ia bisa membuat tembaga menjadi emas
bahwa ia bisa mengubah segala yang buruk menjadi indah
dan apakah jika ia tahu?
ia akan menangis?
dan takkah ia melihat,
bahwa banyak yang terjebak karenanya
bahwa banyak yang menangis, juga tertawa karenanya
ah,………..
andai cinta tahu……..”
Dan Arini pun menangis malam itu, dalam shalat lail yang dilakoninya. Menangis karena ia telah mulai melupakan cinta sejatinya. Menangis karena ibadah yang dijalaninya kini seakan tanpa ruh. Menangis karena kini ia mulai malas menggapai cinta-Nya. Menangis karena ia begitu mencintai si pemilik bibir indah itu. Menangis karena takut cintanya nanti berada pada tempat yang salah.
Arini terus berharap dalam sujud panjangnya, agar Sang Pemilik Cinta tidak marah padanya. Agar dia masih mau memberikan cinta untuknya. Dan agar cintanya pada si pemilik senyum terindah tetap terjaga, murni.
Dan arini pun terus menangis hingga fajar menyapanya lembut, memberi satu tekad.
Pagi itu datang lagi. Masih dengan mentari yang mulai beranjak tinggi. Masih dengan embun yang mulai mengering. Arini pun menikmati pagi itu, seperti biasa. Namun, sebuah tekad pagi ini mampir di benaknya bahwa ia tak akan berhenti di depan rumah sang pemilik bibir manis, juga tak akan menunggu sapaan dan senyuman untuknya.
Sampai di tempat pemberhentian angkot, Arini tertegun. Si pemilik bibir indah itu telah ada di sana. Dan ia, ketika melihat arini, masih tetap tersenyum dengan mata sipit yang nyaris tertelan oleh senyumannya. Lalu ia memandang ke arah jalan raya yang masih sepi tanpa menunggu Arini membalas senyumannya, tanpa sapaan. Dan Arini, hanya bisa tersenyum dalam hati, lalu berdiri agak jauh dari si pemilik senyum terindah untuk menunggu angkot.
“Ya, dan cinta ini akan ku jaga
tapi, takkan ku menangis jika ia hilang terkikis masa
karna ku tahu,
ku masih punya cinta yang takkan meninggalkanku
yang kan selalu ku kejar dan ku harap
karna sekali lagi,
cinta tak ingin
hidup mengalir dan melayang begitu saja,
tanpa ada arah yang menemani”
ditulis saat menunggu detik-detik
menuju umur 15
Sudah pernah dimuat di blogQ yang satu lagi:
aboutansdromeda.multiply.com (dah gak aktip) Wanna More.?
Sabtu, 12 April 2008
mY firSt articLe in BloggEr!!!!!!!!!!!!!!!!
gak tau nih harus ngomong apa?
bingung mau ngomong tentang berita yang lagi hangat sekarang ini,,
tentang pilgub Lampung September nanti,
tentang film FITNA yang menebar ancaman, sampe-sampe YouTube diblokir (yang bikin aku sebel banget),
tentang novel en film "Ayat-Ayat Cinta" yang lagi bener2 booming sekarang ini, padahal sie novelnya dah lama banget rilisnya,
kalo ngomong about artis Indonesia, aku sama sekali gak ngerti, habis, gak demen sama sekali sama artis-artis Indonesia, biarpun ada yang sedikit suka, tapi gak pernah mau ngikutin perkembangannya,
tentang konser FT Island kemaren 30 Maret di Malaysia, yang bikin aku kesel abis,
gimana enggak, habis nggak bisa ke sana? (padahal kalo di Indonesia juga pasti nggak liat, hehe),
mereka kalo gak salah tanggal 12 april nanti mau konser di Thailand, waah....sukses buat mereka, namja-namja cakep.....
habis itu???????????
diriku gak tau lagi mau ngomong apa?
silakan lanjutkan sendiri (hehe) Wanna More.?
bingung mau ngomong tentang berita yang lagi hangat sekarang ini,,
tentang pilgub Lampung September nanti,
tentang film FITNA yang menebar ancaman, sampe-sampe YouTube diblokir (yang bikin aku sebel banget),
tentang novel en film "Ayat-Ayat Cinta" yang lagi bener2 booming sekarang ini, padahal sie novelnya dah lama banget rilisnya,
kalo ngomong about artis Indonesia, aku sama sekali gak ngerti, habis, gak demen sama sekali sama artis-artis Indonesia, biarpun ada yang sedikit suka, tapi gak pernah mau ngikutin perkembangannya,
tentang konser FT Island kemaren 30 Maret di Malaysia, yang bikin aku kesel abis,
gimana enggak, habis nggak bisa ke sana? (padahal kalo di Indonesia juga pasti nggak liat, hehe),
mereka kalo gak salah tanggal 12 april nanti mau konser di Thailand, waah....sukses buat mereka, namja-namja cakep.....
habis itu???????????
diriku gak tau lagi mau ngomong apa?
silakan lanjutkan sendiri (hehe) Wanna More.?
Langganan:
Postingan (Atom)